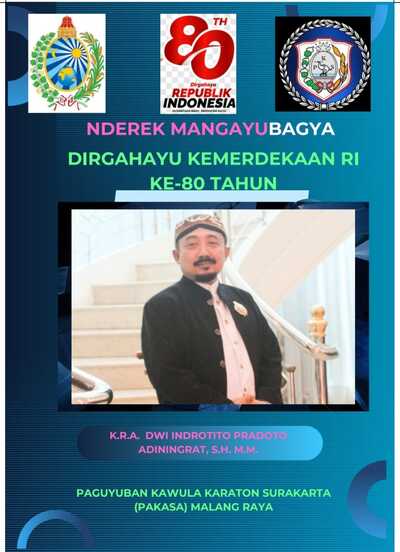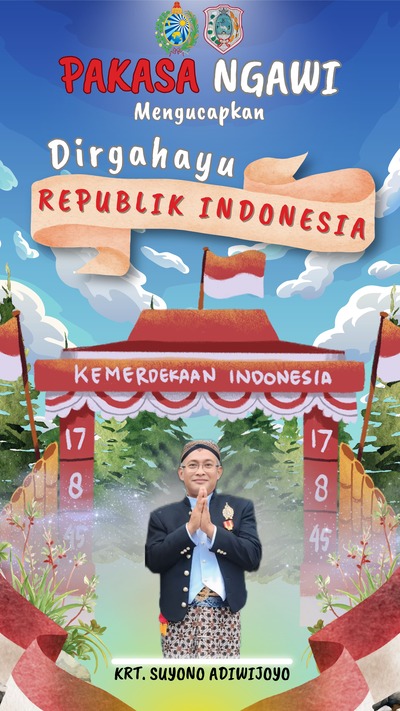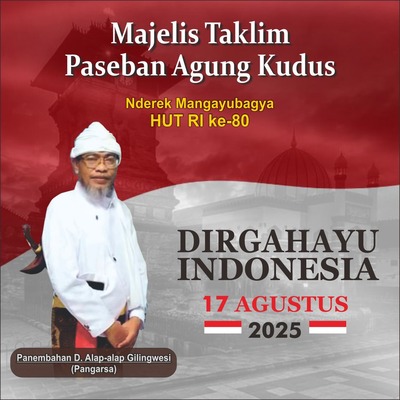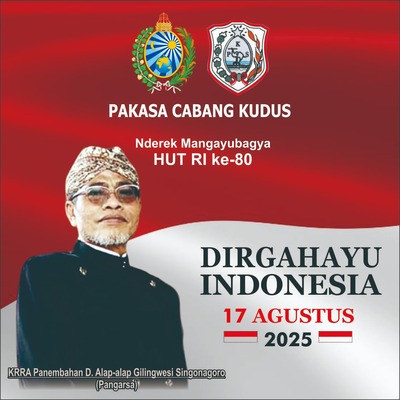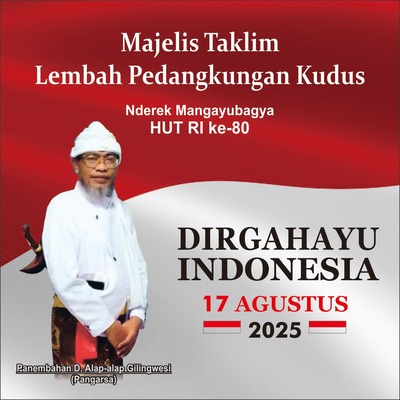“Mencipta” Karya Baru, Lebih 50 Persen Isinya Harus Beda dan tak Memakai Nama Lama
IMNEWS.ID – BAIK ketika memberi sambutan maupun berbicara sebagai narasumber dalam seminar/sarasehan tentang pencatatan karya tari rumpun “Srimpen” di Sasana Handrawina (iMNews.com, 23/8), Gusti Moeng sempat memberi ilustrasi. Bahwa selama 200 tahun Mataram Islam Surakarta berdiri (1745-1945), para leluhur telah “menciptakan” berbagai repertoar (judul) tari kategori rumpun “Bedhayan” dan “Srimpen” .
Proses panjang penciptaan sebagai ekspresi “kekayaan intelektual” dan “rasa” oleh “para pribadi” yang difasilitasi dan dilindungi lembaga “negara” (monarki) Mataram Islam Surakarta itu, tentu harus dimaknai sebagai proses kerja mencurahkan energi intelektual dan spiritual religi/kebatinan (rasa). Dan yang paling esensial dalam proses kerja dua unsur itu, adalah membangun “kerangka baku” karya seni dimaksud.
“Jadi, unsur-unsur gerak baku dari jenis tarian yang masuk kategori (rumpun) ‘Bedhaya’ dan ‘Srimpi’ di Kraton Mataram Surakarta, sudah ada sebelum NKRI lahir (17/8/45). Kalau belakangan beredar video (YouTube) pentas tari menggunakan nama ‘Srimpi’, dan diakui sebagai karya pribadi, di mana letak unsur karya (intelektual) penciptanya? Lalu bagaimana dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kraton?”.
“Menurut saya, aturan tentang hak cipta dan HAKI, tidak bisa membenarkan cara-cara seperti itu. Jadi, unsur gerak baku dalam tari ‘Bedhayan’ dan ‘Srimpen’ apapun jenisnya, sudah ada yang menciptakan dan sudah dimiliki kraton sejak NKRI belum lahir. Jadi, kita tidak bisa membuat karya tari dengan unsur gerak baku yang sudah ada, kita beri nama ‘Bedhaya’ atau ‘Srimpi’, lalu kita sebagai penciptaannya”.

“Tidak boleh seperti itu. Itu melanggar (merampas-Red) hak orang lain sebagai penciptanya. Saya saja, ketika diminta Sinuhun bapak (PB XII) menghasilkan Bedhaya Suka Mulya, hanya berhak disebut sebagai ‘penyusun’ atau ‘penata’. Karena, unsur-unsur gerak baku jenis tari “Bedahayan” sudah ada, dan saya tinggal melengkapi sesuai unsur makna esensi tariannya. Maka, saya tidak berhak sebagai pencipta”.
Demikian pernyataan tandas Gusti Moeng, koreografer tari khas yang sekaligus mantan penari “Bedhaya Ketawang” yang hanya dimiliki Kraton Mataram Surakarta itu itu. Sebagai ilustrasi, eksistensi tari “Bedhaya Ketawang” yang dirawat hingga kini, sekaligus menandakan bahwa Kraton Mataram Islam Surakarta adalah kelanjutan Mataram Islam yang dirintis Panembahan Senapati dan Mataram terakhir di Surakarta.
Sebagai narasumber, Gusti Moeng juga mempertanyakan bagaimana hak kraton secara institusi, karena faktanya lembaga kraton yang memiliki aset karya-karya seni budaya tersebut?. Bila hak cipta tidak tepat disandang, lalu bagaimana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) para tokoh yang telah mencurahkan energi intelektual dan spiritual religi/kebatinannya? Karena Kraton Mataram Surakarta punya banyak Pujangga.
Dengan penandasan beberapa hal dan paparan latarbelakang proses penciptaan karya-karya seni budaya semasa “negara” (monarki) Mataram Surakarta eksis (1745-1945), sebenarnya semakin memprihatinkan publik secara luas. Karena ketika dianalisis lebih dalam, semakin jelas posisi karya seni budaya lembaga kraton dan duduk-perkara pelanggaran dan “perampasan” Hak Cipta dan HAKI di republik ini, selama ini.

Dalam analisis pula, proses penciptaan karya seni budaya yang disinggung Gusti Moeng harus dimaknai sebagai sebuah rangkaian dari tahapan dari awal hingga akhir. Proses panjang itu harus pula dimaknai dengan kerja menciptakan “desain” dan peralatan pendukung yang dibutuhkan. Bila dalam proses penciptaan seni tari, karawitan dan pedalangan, peralatan pendukung bisa berupa gamelan, properti dan sebagainya.
Dalam penciptaan karya “Tosan Aji”, peralatan pendukung dan penciptaan desain menjadi hal penting yang menentukan hasil akhirnya. Karena begitu banyaknya bagian dalam proses penciptaan karya untuk semua jenis seni dalam Budaya Jawa, maka sangat diyakini ada beberapa figur seniman yang terlibat dalam tahapan-tahapan prosesnya. Sangat tidak mungkin sebuah karya hanya dilakukan (diciptakan) seorang saja.
Dengan memahami proses panjang penciptaan karya, yang bisa lebih dari setahun, bahkan bertahun-tahun itu, maka ketika ada insan di abad 19-21 ini mengaku “dirinya” telah “menciptakan” kesenian dalam berbagai jenis berbasis Budaya Jawa dan dalam waktu singkat, rasanya tidak rasional. Karena untuk seni tari saja, sudah lebih dulu ada unsur gerak baku pada “Bedhayan” atau “Srimpen” sebagai “babonnya”.
Karya Tosan Aji, gamelan, wayang, keris dan reog memang sudah mendapat pengakuan sebagai heritage dunia, yang tentu tidak mungkin bisa diklaim sebagai karya perseorangan. Terlebih, bila klaim dilakukan terhadap karya yang masih menggunakan unsur nama lama dan 50 persen unsur bakunya masih tampak jelas sebagai karya tokoh maupun lembaga di masa lalu. Terlebih kesenian wayang kulit “gagrag” Surakarta.

Dalam seni wayang kulit, lembaga “negara” Mataram Surakarta telah menciptakannya begitu beragam elemen isi/bagiannya, lengkap, tuntas dan nyaris sempurna. Di dalamnya ada karya gamelan terbagi dua, Slendro dan Pelog, yang bisa menjadi elemen mandiri. Sebagai elemen mandiri, gamelan juga sudah mencapai tahap final dan sampai pada puncaknya sebagai instrumen musik yang bisa dimainkan secara orkestra.
Melalui proses sangat panjang, gamelan Jawa “gagrag” Surakarta diciptakan sejak abad 14. Karena, saat Islam masuk ke tanah Jawa, elemen metal sudah menjadi karya para Empu pada peradaban Jawa yang lebih tinggi. Selain elemen gamelan yang bisa membentuk seni karawitan, ada elemen karya tatah-sungging yang disebut (anak) wayang, kemudian peralatan pendukung pentas seperti “Kelir”, “debog” dan “blencong”.
Elemen eni suara atau vokal, juga menjadi bagian penting pada satu-kesatuan seni pedalangan wayang kulit “gagrag” Surakarta. Di situ ada “pesinden” atau “widuwati” dan “wiraswara” yang semuanya bisa berfungsi sebagai “gerong”. Fungsi elemen vokal ini, juga bisa dilakukan para seniman “pangrawit” atau “penabuh” berbagai jenis instrumen karawitan iringan pada pergelaran seni pedalangan wayang kulit.
Hal yang lebih penting lagi pada seni pedalangan wayang kulit, adalah elemen “cerita” atau “lakon” yang menjadi sajian pertunjukan bertema atau berkisah dalam urutan struktur di atas “kelir”. Kebutuhan soal inipun, secara baku “negara” (monarki) Mataram Surakarta sudah menyiapkan tema-temanya yang tertulis dalam data manuskrip disebut “Serat”. Para Pujangga Jawa milik Mataram Surakarta, yang menulisnya.

RNg Ranggawarsita yang menjadi abdi-dalem Kraton Mataram Surakarta pada zaman Sinuhun PB IV hingga PB IX, menulis banyak sekali lakon wayang kulit “gagrag” Surakarta. Mulai dari Serat Pustaka Raja Purwa hingga Serat Pustaka Raja Madya (wayang Gedhog). Beberapa Pujangga lain termasuk RNg Jasadipoera hingga Padmosusastra, menciptakan lakon wayang kulit yang diadaptasi dari kitab Mahabharata dan Ramayana.
Dengan mencermati berbagai jenis bagian seni pedalangan wayang kulit yang semuanya sudah “disediakan” (diciptakan), para seniman dalang tinggal “memanfaatkannya”. Elemen kreativitas atau “sanggit” memang perlu, sebagai ruang ekspresi kecerdasan figur dalangnya. Tetapi elemen itu hanya 10 persen, yang tidak rasional bila menghilangkan eksistensi beberapa elemen lain atau 90 persen sajian wayang kulit itu. (Won Poerwono – bersambung/i1)