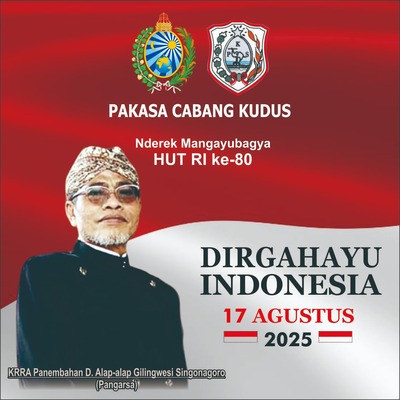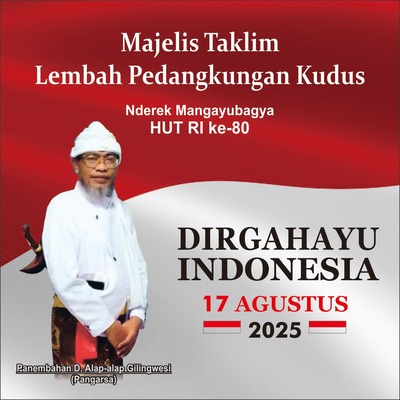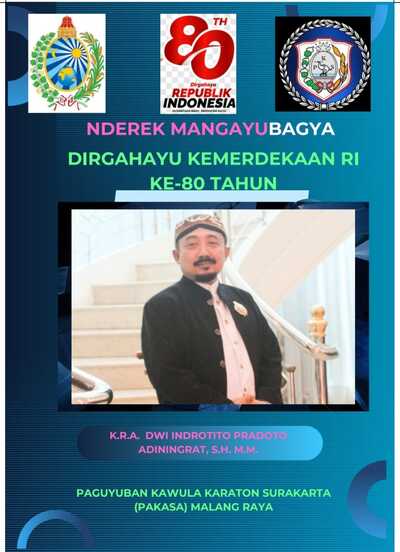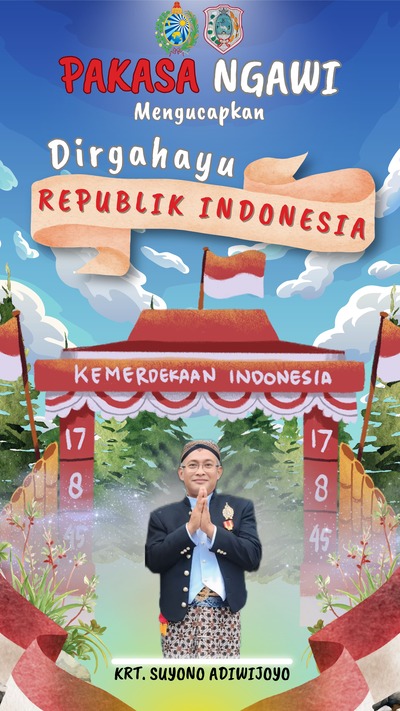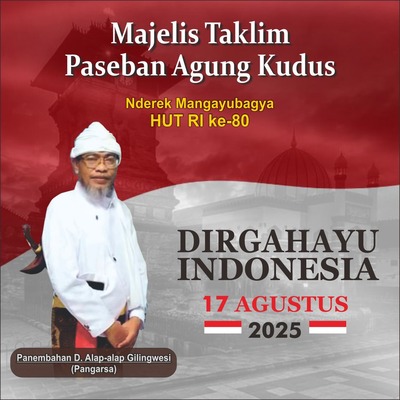Kini, Pentas Wayang Kulit Hanya Jadi Ajang “Parodi”, Dalang Tenggelam oleh Bintang Tamu
IMNEWS.ID – BEGITU memasuki “Pathet Sanga” (9) usai “Brubuh Ngalengka”, Ki Dr Purwadi menandai dengan adegan Kraton Singgelapura, dan Raden Gunawan Wibisana jumeneng nata sebagai Raja bergelar Prabu Bisawarna. Para kerabat yang terlibat dalam perang besar itu, berkumpul dan membahas masa depan. Semua tahapan dari struktur sajian wayang kulit “gagrag” Surakarta klasik konvensional, terujud rapi.
Sementara itu, di Negeri (Kraton) Yawastina yang berdiri setelah perang besar “Bharatayuda”, penerus darah Pandawa bertahta sebagai raja bergelar Prabu Parikesit. Dia sedang berdiskusi dengan para sesepuh yang tersisa, yaitu Raden Anoman dan utusan “Kadewatan”, yaitu Bathara Narada. Di penghujung “Pathet 9” inilah, Ki Dr Purwadi menjadikan jembatan memasuki wilayah “Wayang Madya” sebagai “sanggit”.
“Sanggit” merupakan kreativitas dalang sebagai bentuk kebebasan berpikir dan berekspresi dalam berkesenian, yang dibatasi oleh estetika dan etika. Sementara yang dilakukan Ki Dr Purwadi menyajikan lakon Ramayana hanya dalam durasi sekitar “4 jam” dari pukul 10.00 WIB hingga 01.00 WIB, hanya melakukan “sanggit” lakon dan struktur. Dia “terpaksa” mempersingkat tahapan dan “meminjam nama”.
Durasi pentas yang benar-benar klasik konvensional mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB pagi yang banyak dilakukan para dalang sebelum tahun 1990-an, berangsur-angsur telah berubah. Berbagai faktor penyebab, termasuk aturan, telah merubah “nyaris total” sajian pentas wayang kulit. Sehingga, pertunjukan ini mengalami desakralisasi, demitosisasi, delegitimasi dan dekulturisasi

Berdasar ilustrasi dan sedikit analisis perjalanan seni pertunjukan wayang kulit dalam 4-5 dekade terakhir, Ki Dr Purwadi tampak berusaha mengembalikan “marwah” sajian wayang sesuai keberadaannya. Walaupun, secara jelas sudah tampak “batasan-batasan” yang menghambatnya. Selain durasi terbatas karena alasan aturan izin keramaian, kehadirannyapun hanya dengan daya dukung “serba terbatas”.
Dalam kajiannya sebagai peneliti sejarah dan pelaku seni pedalangan, Ki Dr Purwadi menegaskan bahwa sajian wayang kulit atau “ringgit wacucal” dengan berbagai istilah dan sebutannya, adalah bentuk upacara adat. “Negara” (monarki) Mataram dan lembaga-lembaga serupa yang mendahuluinya sejak Majapahit, melalui proses panjang menciptakan “wayang kulit”, sebagai format ekspresi upacara adat spiritual religi.
Kini, format wayang kulit sebagai upacara adat, yang diadaptasi masyarakat Jawa sebagai doa syukur atas kemurahan Allah SWT, Tuhan YME, sudah berubah “nyaris total”. Karena ekspresi ucapan terima kasih atas kelimpahan berkah dan rezeki melalui panen padi itu, sudah tidak terdapat di kalangan masyarakat desa. Pentas wayang dengan lakon “Sri Mulih” sebagai ekspresi syukur itu, sudah sirna.
Praktik seni pertunjukan wayang kulit yang berangsur-angsur menghilangkan sifat dan unsur sakral dari wujud doa syukur sajiannya (desakralisasi), menempatkan wayang kehilangan sisi “tuntunannya”. Yaitu “tuntunan” bagi manusia untuk selalu bersyukur kepada Tuhan YME, Allah SWT, yang diekspresikan melalui kesenian adiluhung yang berestetika dan beretika, berupa pentas wayang kulit lakon “Sri Mulih”.

Kalangan dalang praktisi seni pakeliran, ditambah “othak-athik” konsep dari sisi keilmuan di lembaga perguruan tinggi seni, melalui proses panjang telah “berhasil” menghilangkan sifat sakral wayang kulit. Sifat sakral yang salah satunya unsur “tuntunan” itu, telah “dirusak” dan disingkirkan oleh para praktisi (dalang) dan akademisi yang menjalankan kurikulum pendidikan yang “disusun pemerintah”.
Cara-cara pihak “kolaboratif” untuk menghilangkan sifat “tuntunan” sajian wayang kulit memang halus, yaitu melalui kurikulum pendidikan seni pedalangan yang disusun. Tetapi, cara-cara kasar proses penghilangan sifat sakral dan “tuntunan” seni wayang, justru dilakukan para praktisi itu sendiri. Jadi, para dalang profesional itu sendiri yang telah “merusak” sumber “sandang-pangannya” (rezeki).
Sayangnya, para dalang praktisi “kawruh” seni wayang kulit tidak sadar dan tidak paham, bahwa “kelakuan” buruk di panggung seni pedalangannya telah menghancurkan nilai-nilai keagungan dan adiluhung yang menjadi sumber rezekinya. Karena, selalu lupa saat para penanggap, pecinta dan pengagum penampilannya bersorak-sorai memujinya karena berhasil menampilakan “atraksi” yang dianggap “menghibur”.
Atraksi “sabet”, pembentukan opini publik tentang Dewa sebagai manusia biasa yang bisa salah, kehadiran bintang-tamu pelawak dan penyanyi, unit musik band/keroncong/campursari dan praktik bercanda di depan “kelir” (layar) melibatkan dalang, bintang tamu dan pesinden sambil berdiri, itu adalah contoh-contoh praktik “perusakan” nilai-nilai “tuntunan” yang sakral transendental dari wayang kulit.

Bercanda di atas panggung seperti yang kini semakin marak terjadi di berbagai tempat hajadan untuk berbagai resepsi hingga perayaan 17-an di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sering memunculkan kata-kata kasar ekspresi “jalanan” yang “urakan”. Ironisnya, ungkapan dengan kata “misuh-misuh” yang sering diucapkan dalam “antawecanan” dan “pocapan”, justru “dipelopori” tokoh dalang (Pangeran) dari kraton.
Karena “pelopor” perusakan nilai-nilai “tuntunan adiluhung” itu justru dari tokoh keluarga kraton, maka sempurnalah sudah upaya “desakralisasi”, “demitosisasi”, “dekulturisasi” dan “delegitimasi” itu. Panggung pertunjukan wayang kulit yang kembali marak di berbagai wilayah dalam rangka apapun, apalagi untuk 17-an ini, kini hanya pertunjukan “parodi”, gabungan unsur musik dan tingkah lucu “urakan”.
Praktik pertunjukan “parodi” lawak yang nyaris total keluar dari batas-batas estetika dan etika Budaya Jawa seperti itu, sudah tidak layak disebut sebagai pelestarian seni Budaya Jawa. Sebab, sisi yang menunjukkan nilai-nilai “tuntunan” di balik nama besar dalang yang ditanggap puluhan juta rupiah itu, sama sekali tidak. Yang tampak hanya dalang bercanda dengan para bintang tamu dan sebagainya.
Dalam sajian wayang kulit seperti itu, properti dan ubda-rampe pementasan wayang kulit serta jalannya pentas, menjadi “hiasan” belaka. Sejumlah nama besar tokoh dalang yang sering tampil melalui YouTube sekalipun, hanya menjadi bagian sajian “parodi” penuh canda-tawa itu. Dia bahkan kalah pamornya dari para bitang tamu pelawak, penyanyi/pesinden dan unsur-unsur lain yang “menempel”.

Setelah menempuh perjalanan waktu dan trend industri seni budaya mulai berganti, sepertinya para dalang praktisi mulai kebingungan saat frekuensi “tanggapan” semakin sedikit, bahkan bagi sejumlah nama dalang sudah habis, “selesai”. Tetapi, mereka tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi? dan tidak tahu persis apa yang menyebabkan?. Bahkan mereka tidak tahu apa solusinya? dan bagaimana mendapatkannya?.
Dalam posisi seperti itu, Ki Dr Purwadi menawarkan sebuah solusi yang mempunyai “multi efek” positif. Salah satunya adalah edukasi yang mengajak para dalang profesional sadar bahwa sumber “kawruh” seni pedalangan “gagrag” Surakarta yang menjadi rumah besarnya”, kini rusak prah dan perlu “direnovasi”. Salah satu cara merenovasinya, harus dimulai dari “belajar” memahami esensi wayang kulit. (Won Poerwono – bersambung/i1)