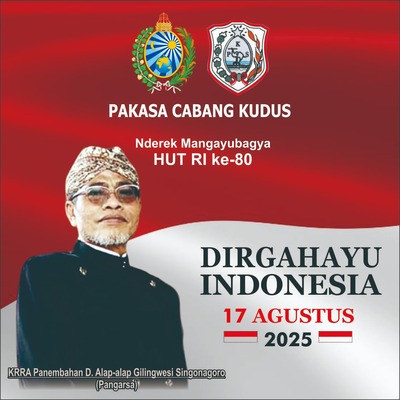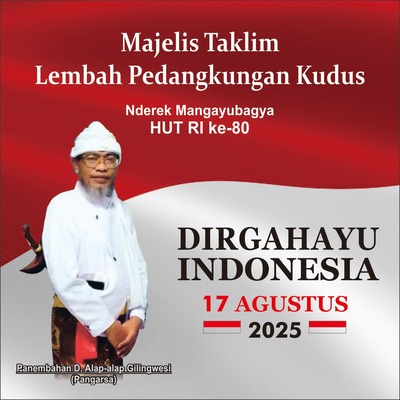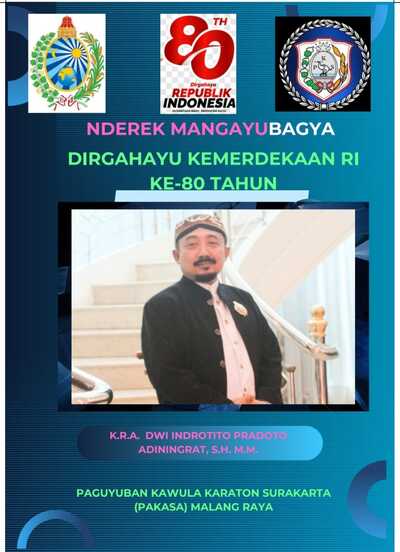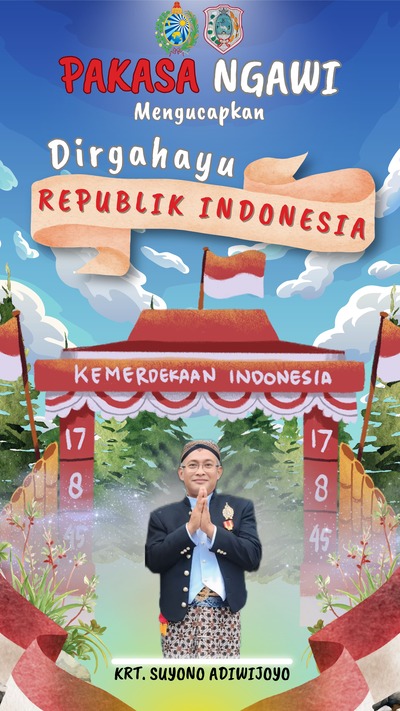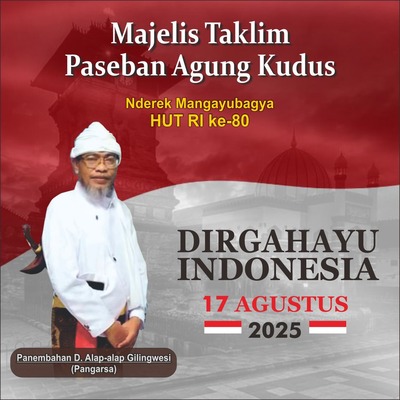Membangun Narasi Positif Sejarah Mataram, Mengembalikan Nilai-nilai Adiluhung Budayanya
IMNEWES.ID – KESEMPATAN menggelar pentas wayang kulit di malam “detik-detik Proklamasi”, 16 Agustus di Kampung Kentungan, Jogja dalam peringatan 80 tahun Kemerdekaan RI ini, adalah momentum sangat strategis. Kesempatan emas bagi dalang Ki Dr Purwadi untuk menjalankan “misi utamanya”, pelan-pelan membangun narasi positif sejarah Mataram (Islam) khususnya Mataram Surakarta.
Bahwa selama menjalankan misi utama harus melalui bagian-bagian lain yang secara sengaja atau tidak sengajar ikut “terbenahi”, bisa disebut sebagai “misi antara”. Karena, kemampuan dan penguasaan “kawruh” seni pedalangan yang lama dipelajari secara autodidak, ternyata menjadi jalan/cara ideal dan tepat untuk mencapai sasaran misi utamanya, yaitu menyingkirkan stigma negatif.
Peran Dr Purwadi yang aktif menyumbangkan pemikiran sejak Bebadan Kabinet 2004 memegang otoritas di Kraton Mataram Surakarta selepas kepemimpinan Sinuhun PB XII, adalah “keberuntungan” bagi banyak pihak. Salah satunya, karena tokoh ini sudah memiliki “sumber penghidupan” yang layak dari tempatnya bekerja sebagai tenaga pendidik di sebuah lembaga pendidikan negeri di Jogja.
Oleh sebab itu, ketika sisa tenaga dan pikirannya dicurahkan untuk menyumbangkan pemikiran solutif bagi Kraton Mataram Surakarta, justru menjadi sarana penyaluran salah satu “dharma” perguruan tinggi secara nyata di tengah masyarakat. Kegiatan ini bahkan berdampak positif, karena dari caranya menyumbangkan “dharma” dengan berbaur langsung di tengah masyarakat adat, banyak didapat “input”.

Input yang dimaksud adalah situasi dan kondisi riil masyarakat yang mungkin sudah berkembang dari saat diteliti beberapa dekade sebelumnya, hingga menjadi teori berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan di kampus. Berikut adalah input mengenai situasi dan kondisi masyarakat adat yang berkait dengan sejarah peradaban Mataram, mengingat ada tujuan ideal di dalamnya yang harus dikawal.
Pada input yang kedua inilah, Ki Dr Purwadi banyak menimba secara langsung di lapangan, karena merasakan sebagai secara partisipasif. Keterlibatannya di berbagai acara dan upacara adat yang digelar Kraton Mataram Surakarta sebagai peserta atau partisipan, telah memberinya pengalaman secara empiris dan keuntungan simbiosis-mutualistik untuk diri (kampus) dan masyarakat adat (kraton).
Oleh sebab, ketika beraktivitas menyumbangkan pemikiran melalui pementasan kesenian wayang kulit dan menulis buku ditambah forum sarasehan “bedah buku” karyanya”, adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Selain rasional, pilihan itu sangat strategis karena disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, tetapi tidak dimiliki orang lain. Seandainya ada orang lain, belum tentu “mau” dan “mampu”.
Perihal “mau”, Ki Dr Purwadi sudah membuktikan atau mewujudkan dengan perbuatan nyata sangat intensif, setidaknya dalam dua dekade terakhir. Bahkan, dia “mampu” melakukannya karena memiliki bekal secara keilmuan yang diperlukan untuk menyumbangkan pemikiran positif, solutif dan futuristik ke depan bagi masyarakat adat di berbagai elemen dan kraton, bahkan bagi publik secara luas.

Kerja adat, kerja keilmuan, kerja “ke-ngelmu-an” dan berbagai jenis kerja ideal dan strategis di dalam bingkai “kawruh” Budaya Jawa yang di dalamnya ada kearifan lokal seperti yang dilakukan Ki Dr Purwadi, memang baru “dia seorang”. Karena, sejak Kraton Mataram Surakarta berada di alam republik mulai 17 Agustus 1945, tidak pernah ada intelektual kampus yang “mau” dan “mampu” (bisa) menjelankan.
Sebut saja Nancy K Florida yang pernah mendokumentasi naskah-naskah kuno aset kraton dalam film di tahun 1980-an, itu karena penugasan dari sebuah yayasan di AS yang bernama Ford Fundation. Dia jelas dibayar mahal untuk menjalankan tugas itu, di luar adanya agenda atau misi lain dari negaranya yang tidak kita ketahui. Sangat beda sekali dengan Ki Dr Purwadi, yang murni inisiatif pribadi.
Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara (Lokantara) Pusat di Jogja itu, punya niat pribadi dan membiayai kegiatannya “membantu” kraton secara swadaya mandiri. Dia “bersolo karier” menyusun rencana dan mengeksekusi rencananya sendiri, walau untuk eksekusi dalam bentuk pentas seni pakeliran, ia mengajak kru pendukung temporalnya. Dan yang jelas, dia berada di luar struktur lembaga kraton.
Yang jelas, memilih seni pakeliran yang menjadi sarana untuk menyumbangkan pemikirannya, adalah pilihan yang cerdas. Karena, kemampuan menyajikan wayang atau mendalang sesuai kaidah lengkap dan urut, nyaris tak dimiliki intelektual kampus lain dari lembaga universitas manapun. Kalaulah ada, belum tentu mau menyumbangkan kepada “kraton” dan masyarakat adatnya secara gratis.

Menyumbangkan pemikiran melalui pementasan wayang kulit, bukan sekadar menjadi cara untuk menyampaikan pemikiran agar sikap dan kerangka berfikir yang salah (negatif) masyarakat luas tentang kraton dan Budaya Jawa berubah. Tetapi ada “misi antara”, yaitu edukasi untuk mengembalikan sifat kesenian wayang yang benar-benar adiluhung, karena praktik di masyarakat selama ini justru sebaliknya.
Kalangan pejabat dan tokoh masyarakat banyak “gembar-gembor” berpidato bahwa seni wayang kulit adiluhung yang harus dilestarikan. Tetapi, praktiknya hampir di semua panggung yang menggelar seni wayang kulit di berbagai tempat luas selama ini, justru “merusak” kesenian wayang. Dari praktik-praktik sejumlah besar dalang “selama ini”, justru telah menghilangkan nilai-nilai adiluhung itu.
Sebagai ilustrasi, pidato para pejabat dan tokoh masyarakat yang melukiskan bahwa seni wayang kulit adalah kesenian “adiluhung” yang bisa menjadi “tuntutanan” sekaligus “tontonan”. Pidato itu justru banyak terjadi pada dekade 1980-1990an, lalu disambung selepas pergolakan sosial krisis ekonomi hingga kini. Pidato itu bahkan disampaikan di acara-acara pentas wayang kulit dan seni lain.
Yang menjadi ironis, setelah acara pidato, pentas wayang kulit dimulai dan di acara “Parekan Limbuk-Cangik” dan “Gara-gara Panakawan”, hadirlah para-pelawak, seni campursari, band dan bahkan penari atau pesinden diminta berdiri di panggung untuk berjoget diiringi campursari atau masuk dangdut. Belum lagi, “antawecana”, “janturan” dan dialog wayangnya, sering diselingi “pisuhan” dan caci-maki.

Yang lebih menyedihkan lagi, ungkapan “caci-maki”, “pisuhan” dan kata-kata “urakan” itu diucapkan seorang figur dalang bergelar “Pangeran” putra-dalem dari kraton. Insiden di panggung kesenian seperti inilah yang sulit diroleransi. Karena insiden itu bisa merusak “peradaban” Budaya Jawa, dan berpotensi lahirnya desakralisasi dan dekulturisasi pada seni wayang kulit, serta delegitimasi Budaya Jawa.
Oleh sebab itu, yang terjadi selama ini sebenarnya adalah praktik menyimpang gelar seni wayang dan sebagainya di berbagai resepsi hajadan di masyarakat. Dari situlah, sebenarnya sifat dan nilai-nilai adiluhung wayang sudah tidak ada. Nilai-nilai “tuntunan” wayang kulit sudah dirusak para seniman dalang itu sendiri, dan Ki Dr Purwadi kini merintis upaya untuk mengembalikannya. (Won Poerwono – habis/i1)