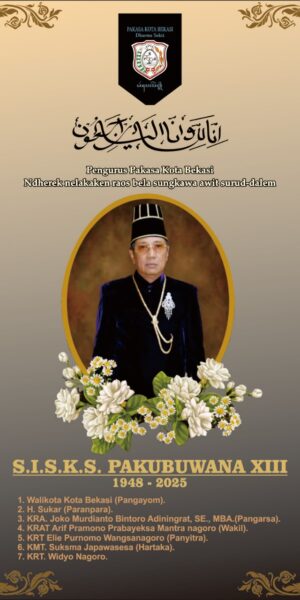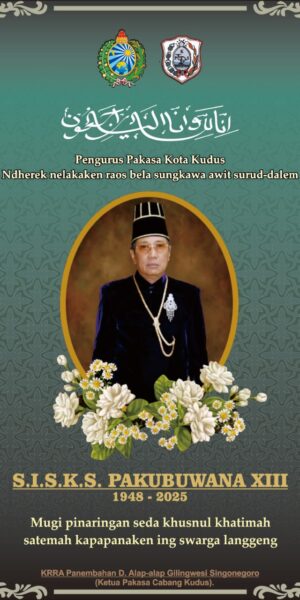Tidak Ada Kekuatan Hukum Bisa Memaksa Pelanggaran Etika “Rekayasa” Putra Mahkota
IMNEWS.ID – PADA seri artikel sebelumnya tertulis dalam sub-judul “Seandainya KGPH Purubaya Benar-benar Sebagai “Putra Mahkota”, Maka…” (iMNews.id, 15/11/2025), adalah bentuk rangsangan untuk berfikir kritis. Setidaknya, menuntun untuk memahami apa makna kata-kata itu. Kalau sudah dipahami kira-kira apa yang dimaksud kata itu, proses penalaran yang sehat menuntun untuk mencari penjelasan di balik itu.
Kalimat “Seandainya KGPH Purubaya Benar-benar Putra Mahkota, Maka….”, adalah kalimat positif yang bisa berarti positif dan negatif. Maka, kalau menggunakan konotasi lawannya yang berarti negatif, bisa berbunyi “Seandainya KGPH Purubaya ‘tidak’ Benar-benar (bukan-Red) Putra Mahkota, Maka….”. Penggunaan kata “tidak” atau “bukan” dalam konteks kalimat itu, juga bisa memberi makna positif atau negatif.

Makna positif dan negatif akan muncul atau menjadi tujuan, tentu bagi pihak diuntungkan dengan makna itu dalam konteks kalimat “Seandainya KGPH Purubaya Benar-benar Putra Mahkota, Maka….” atau yang bermakna sebaliknya. Dan bagi pihak yang tidak menghendaki atau tidak diuntungkan, tentu akan menolak dan memberi penilaian (negatif) terhadap makna kalimat itu. Dalam hal ini, konteks menjadi penentu arah makna itu.
Baca Juga : Memahami di Balik “Bangunan”, “Tahta”, Konsep “Ratu” dan “Bibit, Bobot, Bebet” (seri 3 – bersambung)
Dan, dalam konteks kalimat “Seandainya KGPH Purubaya Benar-benar Putra Mahkota, Maka….” atau yang bermakna sebaliknya, tentu merujuk pada peristiwa yang belakangan ini sedang “panas” di Kraton Mataram Surakarta, dan menjadi perhatian publik secara luas. Tak ketinggalan, rezim penguasa (pemerintah)-pun menaruh perhatian (besar) pada proses suksesi di kraton, bahkan jauh sebelumnya ada “riwayat panjang”.

“Riwayat panjang” perhatian besar rezim kekuasaan terhadap kraton, jelas dimulai dari saat republik ini berdiri di tahun 1945. Saat negara mulai “ingkar” terhadap Pasal 18 ayat 2 UUD 45 dan semua peraturan turunannya, mulai saat itulah melalui rezim kekuasaannya “hadir memberi perhatian besar” dalam hal memperlakukan Kraton Mataram Surakarta hingga “habis-habisan” dan “idak berdaya”, bahkan hingga kini.
Maka, “ontran-ontran” proses suksesi di tahun 2004 jelas sekali “kehadiran rezim kekuasaan” memberi “perhatian besar” dengan mendukung Sinuhun Paku Buwana di luar kraton. Karena, “kekuatan lahir-batin” segenap masyarakat adat yang setia pada pelestarian Budaya Jawa dan masa depan kraton bisa digelorakan, maka kraton dan sebagian besar aset budayanya bisa diselamatkan Bebadan Kabinet 2004 dan LDA.
Tahun 2017 menjadi puncak “ontran-ontran” sisa tahun 2004, yang terus “diupdate” setiap waktu (tahun 2010) oleh oknum-oknum yang “menyediakan diri” menjadi “agen prusak” yang dikendalikan rezim kekuasaan. “Ontran-ontran” yang didukung 2 ribu polisi dan 400 tentara hingga disebut “insiden mirip operasi militer” itu, berlangsung sampai 6 tahunan dan bisa melahirkan SK Kemendagri (No.430-293 Tahun 2017).
Baca Juga : Memahami di Balik “Bangunan”, “Tahta”, Konsep “Ratu” dan “Bibit, Bobot, Bebet” (seri 2 – bersambung)
SK Kemendagri tentang pengelolaan kraton itu, salah satu poinnya menunjuk KGPH Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Maha Menteri. Kewenangan pada SK Kemendagri yang dikuatkan dengan SK Kemenbud No. 10596/MI.I/KB.10.03/2025 bertanggal 10/11/2025 itu, menjadi dasar KGPH Tedjowulan menganulir peristiwa “klaim sah” sebagai Sinuhun PB XIV, termasuk yang terjadi di Pendapa Sitinggil Lor, Sabtu (15/11).

Tetapi, bukan soal SK Kemendari yang menunjuk KGPH Tedjowulan sebagai Maha Menteri menjadi persoalan penting yang berkait dengan kalimat berkonotasi positif dan negatif di atas. Melainkan, SK itu telah disalahgunakan Sinuhun PB XIII dan kelompoknya untuk melahirkan beberapa “penyimpangan”. Celakanya, produk yang menyimpang itu diyakini publik sebagai kebenaran sesuai aturan, padahal keliru dan sesat.
Yaitu, “perbuatan melawan hukum” Sinuhun PB XIII yang menyalahgunakan SK Kemendagri untuk mengangkat sang istri menjadi “prameswari” (permaisuri) dengan gelar “GKR”. Padahal, istri tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat, baik dari sisi hak (asal-usul) adat atau “nazab”, maupun mekanisme adat untuk mendapatkannya. Karena gelar “sulapan” (GKR) itu, lalu digunakan untuk menentukan “Putra Mahkota”.
Maka dari sinilah kemudian bisa mencermati bagaimana kalimat “Seandainya KGPH Purubaya Benar-benar Putra Mahkota, Maka….” dari sisi positif, dan begitu juga sebaliknya dari sisi “yang suka” negatif. Makna kalimat utuh keseluruhan yang bisa dipahami, bisa berbunyi “Seandainya KGPH Purubaya Benar-benar Putra Mahkota, Maka Tidak Akan Terjadi Pro-kontra”, atau polemik panjang dan “ontran-ontran” yang tidak perlu.
Tetapi, fakta-fakta hukum sudah terjadi seperti disebut dalam putusan Mahkamah Agung (MA) No.1950 K/Pdt/2022 yang dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Surakarta dengan turunan No.87/Pdt. G/2019/PN Ska yang dilaksanakan 8 Agustus 2024. Putusan itu telah mengukum semua pihak yang digugat perdata dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sekaligus menggugurkan status “GKR” (permaisuri) dan “Putra Mahkota”.

Karena fakta hukum putusan MA seperti itu, maka konstruksi kalimat yang lengkap dan rasional pasti akan menjadi pertanyaan “Apakah KGPH Purubaya Benar-benar Putra Mahkota?….”. Karena jika benar, tidak akan terjadi polemik pro-kontra seperti sekarang. Bahkan beberapa tokoh yang disebut dalam putusan MA, tidak perlu mengajukan “gugatan”, karena putusan gugatan itu justru menegaskan otoritas eksisteni LDA.
Baca Juga : Memahami di Balik “Bangunan”, “Tahta”, Konsep “Ratu” dan “Bibit, Bobot, Bebet” (seri 1 – bersambung)
Dengan memahami kronologi dan “penyalahgunaan” SK Kemendagri dan lahirnya status “GKR” (permaisuri) dan asal-usul “Putra Mahkota”, ditambah “bukti wasiat” Sinhun PB XIII, maka sumber masalahnya menjadi jelas. Dan peristiwa “jumenengan” yang terjadi Sabtu (15/11), menjadi kegiatan sia-sia yang “membodohi” diri dan publik, mengedukasi tentang “kebohongan” kepada publik, dengan sajian “drama” tanpa nalar dan etika.

Memang, pahit-getir yang dirasakan Kraton Mataram Surakarta dan sempat dicatat berbagai termasuk Harian Suara Merdeka (sebelumnya) dan iMNews.id (kini), termasuk peristiwa “ontran-ontran” yang terjadi nyaris tak ada yang bisa “dipaksa” selesai oleh “kekuatan hukum” positif. Karena, hampir semua jenis pertikaian itu dianggap masuk kategori pelanggaran etika, yang selalu “dipaksa” menjadi sebatas masalah keluarga.
Termasuk, berbagai “kekayasa” untuk melahirkan posisi “GKR” yang dijadikan dasar menentukan “Putra Mahkota”. Rekayasa itu belum tentu sepenuhnya berada dalam wilayah pelanggaran etika, tetapi kalau sudah sampai pada “dokumen pribadi” yang diatur oleh hukum negara yang direkayasa, tentu bisa memenuhi dalil-dalil perbuatan melawan hukum. “Rekayasa dokumen” ini, bisa menimbulkan akibat hukum di berbagai ruang. (Won Poerwono – bersambung/i1)