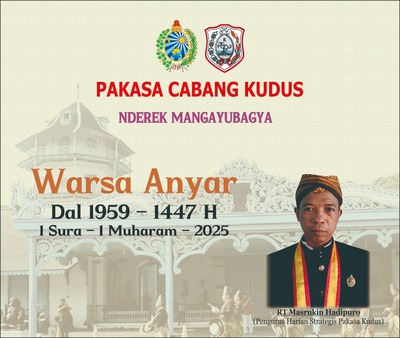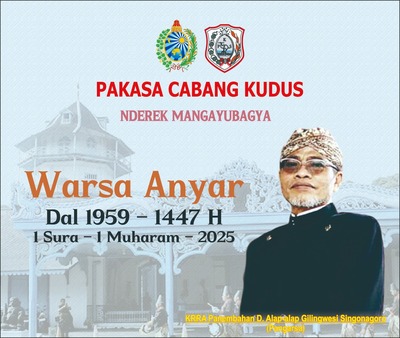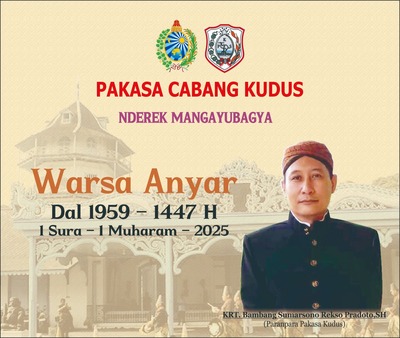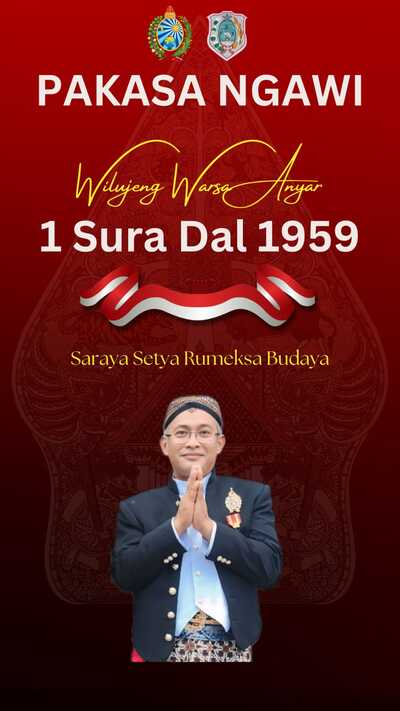Tak Ada yang Bisa Menjelaskan “Rasa” dan “Makna”, Selain Berbahasa “Krama”
IMNEWS.ID – MENDENGARKAN sambutan Gusti Moeng yang menjadi penutup upacara adat peringatan berdirinya “Nagari Surakarta Hadiningrat” ke-289 tahun (Jawa) pada 17 Sura Dal 1959 di tahun 2025, Sabtu (12/7) lalu, serasa menikmati ungkapan kata-kata berirama yang frekuensinya rendah, menenteramkan. Hanya sedikit lebih tandas dari alunan tembang Macapat.
Maklum, tembang Dhandhanggula yang melukiskan pindahnya Kraton Mataram dari Plered, Kerta, Kartasura hingga Surakarta dari “Serat Pindah Kedhaton” yang didendangkan Nyi KMT Eka Laras, adalah gaya ekspresi seorang pesinden. Maka, kata demi kata dari syair tembang itu lebih menonjol rasa yang lahir dari “cengkok” dan “gregelnya”, karena syair Macapat dituturkan “gendhing”.
Kesimpulan dan intinya, kalimat dalam esensi bertujuan apapun, ketika menggunakan ekspresi cara bertutur yang tepat dalam bingkai berbahasa Jawa “krama” apalagi level “inggil”, memiliki daya dan pengaruh psikis luar biasa. Mirip mantra hipnotis ketika dituturkan KRMH Sapardi Rio Yosodipuro (juru penerang budaya di akhir Sinuhun PB XII) atau KPA Winarno Kusumo (Wakil Pengageng Sasana Wilapa).
Dan dari pengamatan iMNews.id, penggunaan Bahasa Jawa di berbagai acara dan tempat terutama lingkungan kraton menunjukkan, berBahasa Jawa “Krama” memang banyak memberi pengaruh psikis karena faktor subjektif tokoh yang mengekspresikan. Karena, kekayaan kata, istilah dan makna dalam berBahasa Jawa “Krama”, punya kekuatan membuat suasana, luruh, damai dan “tenteram”.

Kemahiran dua tokoh “juru penerang budaya” kraton di atas, mampu mengekspresikan apapun tetap terdengar dan “terasa” santun, datar dan indah dalam Bahasa Jawa (tutur) “Krama Inggil”. Tetap “luruh”, jauh dari kesan marah, kasar apalagi liar (urakan-Red). Sehingga baru jelas beda rasa dan maknanya, andai kata “cumantaka” diekspresikan dengan mata melotot, sambil menggebrak meja.
Mungkin ada tokoh lain sebanding yang pernah muncul sebelumnya, tetapi iMNews.id baru bisa mencermati dua nama tokoh abdi-dalem di atas. Keduanya mampu mengekspresikan atau mengeksekusi kekayaan kata, istilah dan makna yang yang terkumpul dalam Budaya Jawa dengan “berbahasa”. Sedang para Pujangga Jawa Surakarta yang mengumpulkan, merumuskan, menginterpretasikan dan menulis.
Walau tak belajar secara khusus soal “berekspresi” dan “mengeksekusi” seperti kedua tokoh penting di Sanggar Pasinaon Pambiwara di kraton itu, namun apa yang dikespresikan Gusti Moeng dalam “makna” dan “rasa” bahasanya sudah jelas yang dimaksud. Ungkapan agak ketus saat menyebut kata “tuli”, tak terdengar tajam karena terbalut dalam bahasa “krama” dan sesuai dengan “kapasitasnya”.
Namun, bertutur dalam bahasa Jawa “krama” apalagi “krama inggil” untuk mengeksekusi dan mengekspresikan kekayaan kata, istilah dan makna dalam Budaya Jawa, memang tidak tepat jika dilakukan di luar konteks forumnya. Tetapi dalam berBahasa Jawa, masyarakat yang masih merawat kekayaan bahasa dan budaya itu sangat paham soal kapan, di mana dan kepada siapa bahasanya digunakan.

Sadar kaidah “empan-papan” masih banyak dimiliki masyarakat Jawa dalam berBahasa Jawa. Artinya, tak hanya masyarakat Jawa dalam berekspresi menggunakan bahasanya, dalam lingkungan masyarakat etnik lain terutama saat berada di “forumIndonesia”, harus cermat dan cerdas pula untuk berbahasa. Masyarakat yang memahami Budaya Jawa, mempertimbangkan sampai sejauh itu penggunaan bahasanya.
Di “forum masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta”, hal-hal seperti itu sudah seharusnya dipahami benar. Karena, label Kraton Mataram Surakarta sebagai sumbernya Budaya Jawa, melekat di setiap pundak setiap pribadi insan warga di dalamnya. Publik secara luas di luar “forum” itu, menaruh harapan besar dan keyakinan, bahwa tiap insan warga di dalamnya menguasai “kekayaannya”.
Publik secara luas meyakini, tiap insan di dalam “forum masyarakat adat” termasuk Pakasa, apalagi Pasipamarta dan Sanggar Pasinaon Pambiwara, memiliki pemahaman dan penguasaan yang lebih terhadap Budaya Jawa, apalagi sekadar berBahasa Jawa “krama ingggil”, dibanding orang lain/luar. Di sinilah letak tanggungjawab bagi setiap pribadi insan masyarakat adat dituntut untuk selalu “bisa”.
Maka, menjadi aneh seandainya ada kegiatan upacara adat Jawa apakah itu haul (khol) di wilayah etnik Jawa, apalagi punya label Pakasa yang artinya elemen masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta, terdengar menggunakan “bahasa aneh” sebagai pengantarnya. Tidak rasional dan tidak ideal, kalau “forum Budaya Jawa” itu, menggunakan pengantar di luar Bahasa Jawa “krama”.

KP Budayaningat, “dwija” Sanggar Pasinaon Pambiwara menegaskan, akan lebih elok dan lebih meyakinkan seandainya di setiap forum dan acara bernuansa Budaya Jawa, di lingkungan masyarakat Jawa dan di wilayah etnik Jawa, selalu menggunakan bahasa pengantar “Basa Jawa Krama” (inggil-Red). Bahkan menurutnya, wajib berBahasa Jawa “krama” (madya-inggil) dan menguasai Budaya Jawa.
Kalau ada alasan, “Kami ini orang pesisir. Ya seperti inilah kami bertutur-kata”, pernyataan itu memang lugas, mengakui apa adanya. Namun, itu bukan pernyataan seorang yang mengaku atau punya label “abdi-dalem” Kraton Mataram Surakarta. Terlebih mengaku sebagai warga atau malah sebagai Pangarsa Pakasa Cabang. Karena, dari sisi kapasitas sebagai abdi-dalem Pakasa, sungguh tidak sesuai.
Hal-hal seperti inilah, wujud realita situasi dan kondisi sesungguhnya yang ada di kalangan masyarakat adat khususnya di elemen Pakasa cabang, yang daya dukung legitimatifnya menempati porsi sekitar 60 persen dari keseluruhan masyarakat adat. Perkembangan luar biasa ini memang agak “lepas” dari kesiapan pihak pemegang otoritas di kraton, akibat kesibukan dan adanya perubahan.
Oleh sebab itu, perkembangan elemen masyarakat adat menjadi tantangan tersendiri bagi kalangan pemegang otoritas di kraton. Kebutuhan bekal pengabdian atau “pasuwitan”-pun, tentu juga menjadi tantangan terpisah yang harus diperhatikan penanganannya, segera. Untuk mengatasi ini, memang ada kerja “solutif partial” dan ada kerja-sama antara berbagai pihak dan berbagai elemen.

Usulan KP Budayaningrat perlunya ada tim yang ditugaskan menjadi penyuluh keliling di cabang-cabang Pakasa melakukan pembelajaran “kawruh” Budaya Jawa terutama “kawruh Basa Jawa”, itu sangat tepat, ideal dan mendesak. Kebutuhan itu bisa segera dieksekusi dan dijalankan, mengingat belasan Pakasa cabang sudah menyatakan siap “bekerja-sama”, menerima tim, bahkan “sangat membutuhkan”.
Tata-laksana dan eksekusinya memang sangat tergantung dari pihak pemegang otoritas di kraton. Namun, sebaiknya antusias masyarakat adat yang menggelar berbagai acara dan upacara adat dalam suasana Budaya Jawa, tak perlu berlarut-larut “salah-kaprah” dan semakin jauh “menyimpang”. Menguasai dan memahami hal-hal baku dari budayanya, khususnya penggunaan “Basa Jawa Krama”, adalah wajib. (Won Poerwono -habis/i1)