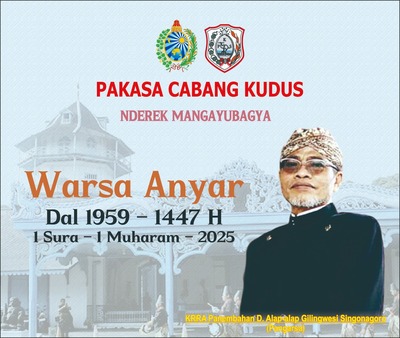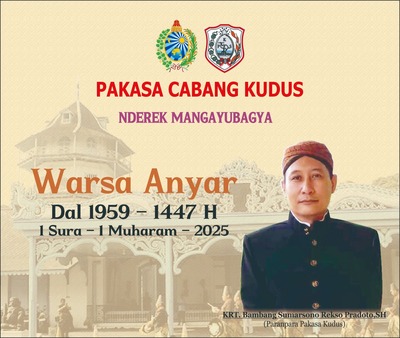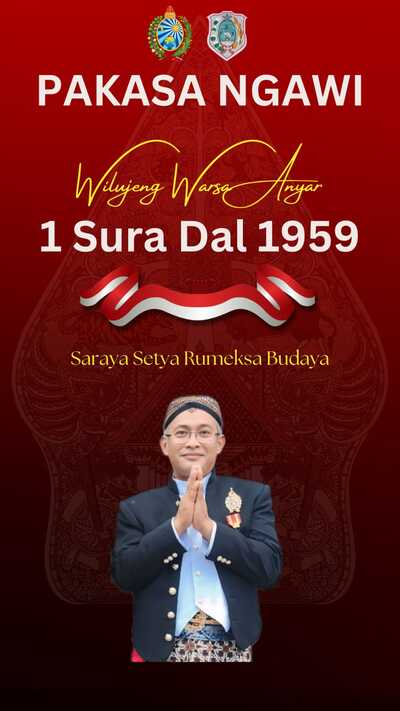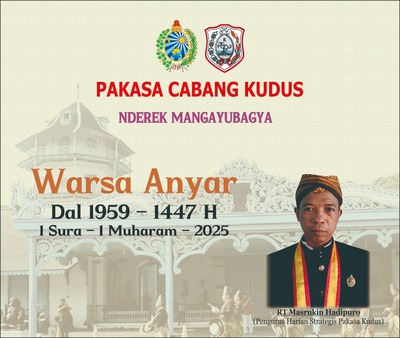“Proses Pemiskinan” Kawruh Budaya, yang “tak Disadari” Masyarakat Jawa
IMNEWS.ID – KESANGGUPAN dan kesiapan KP Budayaningrat dan beberapa figur otoritas Bebadan Kabinet 2004 Kraton Mataram Surakarta memberi “solusi pintas”, perlu didukung semua pihak, baik di internal maupun eksternal. Solusi “terabas” itu penting dan mendesak untuk mengatasi “kesenjangan”, antara realitas penguasaan dan pemahaman “kawruh” Budaya Jawa dan tuntutan ideal dan rasional.
Disebut “solusi pintas” atau “terabas”, karena solusi untuk mengatasi kesenjangan itu kecil kemungkinannya ditembuh melalui jalur ideal yang lebih rasional. Yaitu mulai dari menyarankan, mengajak atau bahkan “mewajibkan” bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi bagian masyarakat adat, tetapi melalui mekanisme prosedur menjadi siswa sanggar atau semacam jalur diklat resmi.
Kemungkinan bisa menempuh mekanisme prosedur pembelajaran resmi lewat Sanggar Pasinaon Pambiwara kecil persentasinya, karena harus meluangkan waktu selama 6 bulan untuk belajar di kelas. Sementara, lokasi cabang sanggar baru ada di satu kota di Jateng (Semarang) dan 2 atau tiga kota di Jatim, selain yang ada di punjer, yaitu “kampus/sanggar” Marcukunda, Kraton Mataram Surakarta.
Selain jarak lokasi lembaga sanggar edukasi, warga Pakasa di berbagai cabang rata-rata didominasi usia di atas 40 tahun yang sudah sibuk dan habis waktunya “mencari nafkah”. Apalagi, selama ini di kalangan masyarakat adat sendiri masih ada beranggapan, bahwa menjadi abdi-dalem di kraton dan berurusan dengan soal adat, tradisi dan budaya, adalah urusan orang tua atau yang sudah dewasa.

Upaya mengembalikan kemampuan menguasai dan memahami “kawruh” Budaya Jawa dan berbagai hal pelengkapnya, jelas terkendala oleh anggapan keliru semacam itu. Ini yang memperparah proses degradasi dan erosi “kawruh” budaya di kalangan masyarakat adat sendiri, terlebih di tengah masyarakat luas. Ada dua potensi ancaman yang harus diatasi bersama, terutama oleh masyarakat adat itu sendiri.
Anggapan keliru tentang urusan adat, tradisi dan budaya asalah urusan orang dwasa, jelas menjadi potensi ancaman semakin berkurangnya daya dukung legitimatif. Karena itu berarti, proses regenerasi jelas tidak mungkin terjadi, atau setidaknya macet atau kurang lancar. Anggapan seperti itu harus diedukasi untuk dihilangkan, dengan cara-cara yang sudah dicontohkan Pakasa Cabang Kudus.
KRRA Panembahan Didik Alap-alap Gilingwesi Singonagoro kini mulai mewajibkan warga Pakasa Cabang Kudus mengajak anak-cucunya di berbagai kesempatan upacara adat dan budaya, salah satu tujuannya upaya mengembalikan penguasaan dan pemahaman “kawruh” Budaya Jawa dari salah satu sisi. Yaitu sisi pengkaderan atau penyiapan generasi penerus, agar yang sudah dibangun Pakasa cabang, tidak putus.
Salah satu hal urgen yang mulai dibangkitkan semangat untuk mengembalikan kemampuan penguasan dan pemahaman itu itu, adalah ruang edukasi yang paling ideal dan sesuai situasi dan kondisi saat ini. Yaitu seperti yang ditawarkan KP Budayaningrat, yang menyatakan siap ditugaskan menjadi “penyuluh budaya”. Dia menyatakan siap seandainya kraton membentuk tim dan menugasakannya di dalam tim itu.

Solusi “pintas” atau “terabas” dengan berkeliling di tiap pengurus Pakasa cabang memberi penyuluhan atau edukasi, karena disadari adanya kendala berupa mekanisme prosedur ideal di atas yang tidak mungkin ditempuh. Sementara, antara penguasaan dan pemahaman “kawruh” dengan skala ideal tuntutan praktik dalam kehidupan sehari-hari, terlampau jauh berjarak.
KP Budayaningrat setuju dan bisa mendukung, kalau dalam setiap acara seni, budaya, tradisi dan upacara adat Jawa terutama di luar kraton, wajib menggunakan bahasa pengantar Jawa dan “krama”, “madya” hingga “inggil”. Selain media komunikasi, juga perlu diedukasi tatacara berbusana adat Jawa, kesesuaian dan kelengkapan penguasaan “kawruh”nya secara cukup, agar “jumbuh” dengan berbagai hal.
“Saya setuju kalau ada acara seni, tradisi, budaya dan upacara adat Jawa, wajib menggunakan bahasa pengantar Bahasa Jawa. Kalau ada acara dalam kerangka Budaya Jawa, tetapi bahasa pengantarnya bukan Bahasa Jawa, ya terdengar lucu dan aneh. Apalagi, yang punya kegiatan Pakasa, yang dipandang masyarakat luas sebagai organisasi masyarakat adat kraton”.
“Jadi, sebaiknya di setiap acara seni, budaya, tradisi dan upacara adat yang digelar masyarakat Jawa dan wilayah Jawa, ya wajib menggunakan Bahasa Jawa. Apalagi pidato, sambutan dan pengarahan diberikan orang-orang penting seperti Lurah, Camat, Bupati atau bahkan Ketua Pakasa. Rasanya wajib berbahasa Jawa, krama madya dan inggil,” tandas KP Budayaningrat.

Perihal kesiapan KP Budayaningrat untuk ditugaskan berkeliling di kalangan Pakasa cabang memberi “penyuluhan” edukasi dalam penguasaan dan pemahaman “kawruh” Budaya Jawa, menjadi tantangan yang patut disambut baik, khusunya bagi warga masyarakat adat. Karena, lebih 10 cabang Pakasa yang pernah dimintai tanggapan iMNews.id, semua menyatakan setuju dan mendukung.
Bahkan, Pakasa Cabang Trenggalek, Cabang Ponorogo dan Cabang Jepara menyatakan sangat membutuhkan edukasi itu, mendesak untuk dipenuhi. Namun, KP Budayaningrat bisa memahami kalau semangat dan niat baik ini, tergantung pada otoritas pimpinan Bebadan Kabinet 2004 sekaligus Pangarsa Lembaga Dewan Adat dan Pangarsa Pakasa Punjer yang berwenang mengizinkan.
Kini, situasi dan kondisi penguasaan “kawruh” Budaya Jawa dan pelengkapnya di kalangan masyarakat luas khususnya elemen Pakasa cabang, memang dalam level “memprihatinkan”. Padahal, masyarakat adat di cabang-cabang Pakasa ini yang banyak memiliki kegiatan pelestarian Budaya Jawa untuk menjaga kelangsungan kraton. Organisasi Pakasa-lah yang memiliki potensi daya dukung legitimasi dalam jumlah besar.
Oleh sebab itu, solusi “pintas” dengan berkeliling menyuluh dan mengedukasi untuk penguasaan berbagai “kawruh” dalam Budaya Jawa, sepertinya paling tepat dan ideal dilakukan, segera. Setidaknya, langkah itu bisa memperpendek jarak senjang antara kebutuhan praktik dan penguasaan materinya. Sambil menunggu proses regenerasi dan sistem pembekalan yang cukup untuk kebutuhan itu.

Dari tiga peristiwa di atas, sebenarnya masih ada banyak peristiwa dalam suasana seni, budaya, tradisi dan adat Jawa yang sering “disentil” Gusti Moeng dalam berbagai kapasitasnya. Pertanyaan Gusti Moeng “Saya harus menggunakan Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ini?. Bahasa campuran saja ya, agar mudah diterima”. Itu “tamparan keras” bagi “wong Jawa” yang sadar siapa jatidirinya.
Terlebih, sentilan itu disampaikan saat memberi sambutan di upacara adat khol atau haul yang digelar warga Pakasa cabang di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka berada wilayah sebaran Budaya Jawa yang mayoritas penduduknya masyarakat etnis Jawa. Ironis, memang. Tetapi itulah realitas faktual kini. Erosi dan degradasi penguasan kawruh Budaya Jawa, jelas. Tetapi, sadarkah itu sebagai proses “pemiskinan”?. (Won Poerwono – bersambung/i1)