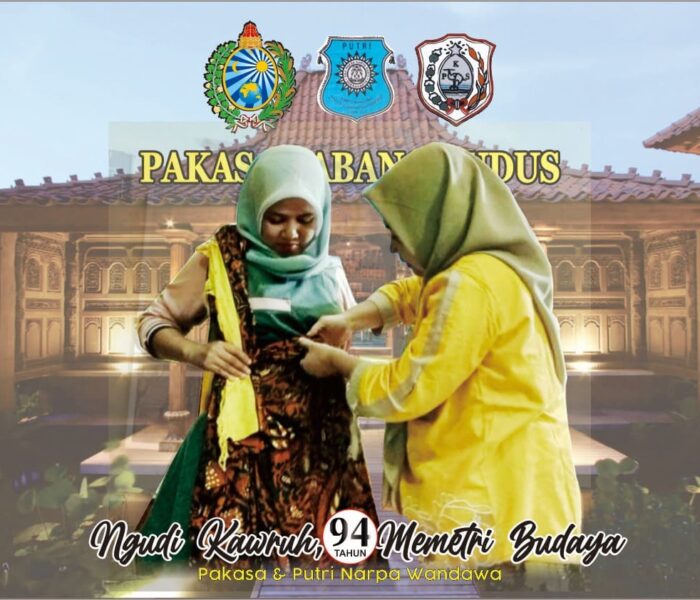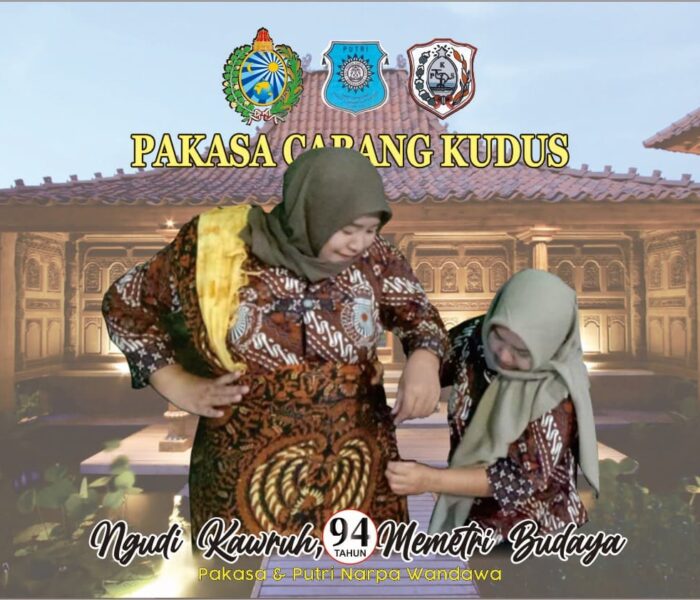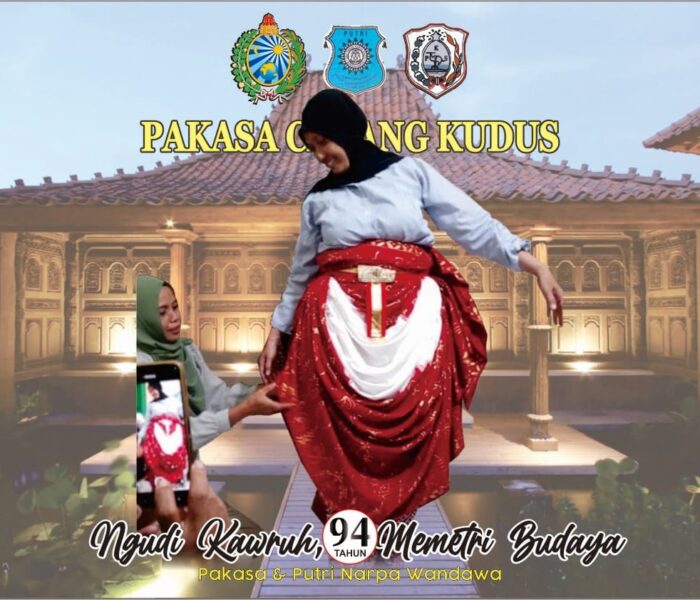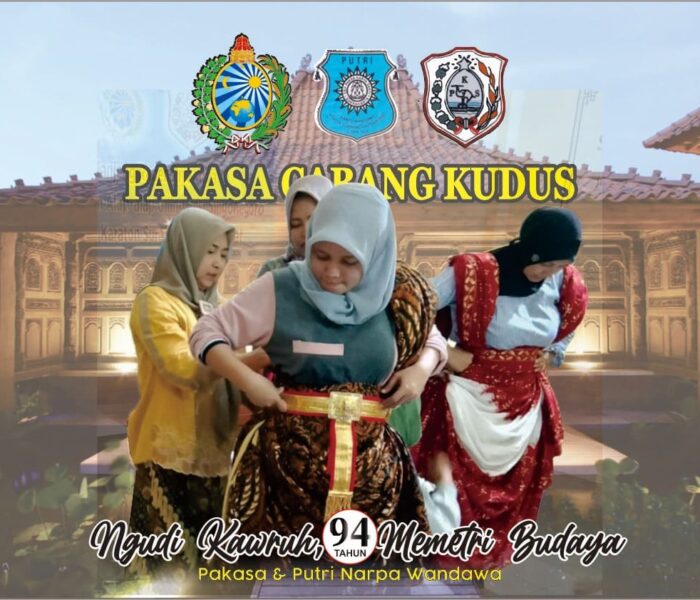Sikap Berkeseniannya Sudah Terlanjur Dihitung dengan Standar Industri Seni
IMNEWS.ID – “WAYANG kulit adalah upacara adat yang sakral”, begitu pernyataan singkat dan tandas Ki Dr Purwadi. Pernyataan itu tentu terarah pada kesenian wayang kulit purwa atau seni pertunjukan pakeliran di tempat asalnya, Kraton Mataram Surakarta, untuk “ringgit wacucal gagrag” Surakarta. Jadi, sama halnya dengan berbagai jenis kesenian produk Budaya Jawa yang bersumber dari kraton, dia adalah sarana ritual.
Sarana ritual adalah bagian penting dari upacara adat. Bahkan, ketika kraton menggelar pentas wayang “ruwatan” untuk menyambut bulan “Ruwah” atau musim “sadranan”, “ringgit wacucal” itu murni aktivitas upacara adat. Begitu pula, ketika kraton menggelar pentas wayang kulit menyambut atau di malam tanggal 10 Sura atau Asyura, sebagai ekspresi religi untuk menghormati Nabi Muhammad SAW karena cucunya wafat.
Karena menjadi bagian dan wujud upacaranya sendiri, maka kesenian wayang kulit bagi kraton merupakan karya peradaban yang sudah sampai puncaknya, lengkap, urut dan tuntas. Struktur sajian gendhing iringan sesuai atau paralel dengan struktur sajian cerita. Ibarat urutan perjalanan hidup manusia, dimulai dari lahir (pembukaan) atau “bedhol kayon”, aktivitas kehidupan hingga “tancep kayon” (penutupan) akhir hayat.
Dalam struktur ceritanyapun, bagi kalangan dalang profesional penganut idealisme wayang konvensional klasik baku yang “diajarkan” Kraton Mataram Surakarta antara lain melalui “Sanggar Pawiyatan Dalang Kraton (Mataram) Surakarta”, juga mengalir urut. Dari “jejer sepisan” pada Pathet Enem (6), “jejer” kedua dan “Perang Kembang” pada Pathet Sanga (9), lalu “Gara-gara” dan “jejer” ketiga (terakhir).
“Jejer” ketiga pada bagian “Pathet Manyura” yang sudah punya standar baku sebabgai penutup, yang menurut Ki Dr Purwadi harus ada adegan yang melukiskan “happy ending”. Di bagin akhir inilah oleh para guru dalang atau dalang senior di atas generasi Ki Anom Suroto dan Ki Manteb Soedharsono, pasti diisi sajian anak wayang yang disebut “Golekan”. Sajian ini adalah isyarat dalang untuk “menantang” para penontonnya.
Tantangannya, adalah agar para penonton “nggoleki” atau mencari makna dan esensi yang tersirat dari jalannya lakon yang dipentaskan dari awal hingga akhir. Sejak dulu, lakon atau judul atau tema sajian wayang kulit pasti sudah disebutkan, karena permintaan yang “nanggap”. Lakon atau tema bisa memandu para penontonnya menangkap memahami inti pesan yang disampaikan para tokoh wayang di atas “kelir”.

Ilustrasi di atas adalah tata-laksana sajian pentas wayang kulit standar klasik baku konvensional “gagrag” Surakarta yang begitu idealistik. Semua syarat itu bisa tersaji baik, lancar, pilah dan jelas atau “gamblang”, jika figur atau tokoh seniman dalangnya benar-benar punya kemampuan di atas rata-rata. Bahkan, dalang yang punya komitmen untuk memegang teguh standar sajian profesional yang idealistik itu.
Atas dasar berbagai persyaratan itu, maka publik secara luas bisa membandingkan bagaimana seni pertunjukan wayang kulit disajikan di “zaman keemasan wayang” menjelang 1980 hingga menjelang abad 21, dengan sajian periode 1945-1970-an dan sajian sebelum 1945. Apalagi dibandingkan dengan sajian wayang mulai tahun 2.000-an hingga kini, karena dari tiap periode itu ada tokoh dalang yang bisa dibandingkan.
Dari beberapa periode itu, Ki (KRTH) Anom Suroto Lebdonagoro dan Ki (KRT) “Wignyo” Manteb Soedharsono yang sudah almarhum itu, telah menikmati sukses di “zaman keemasan wayang” periode menjelang 1980 hingga menjelang abad 21. Keduanya, telah memulai proses kreatif berkesenian di jalur seni pedalangan secara “otodidak” sebelum tahun 1970-an, yang dulu dikenal dengan istilah “nyantrik” dan “ngenger”.
Dua istilah di atas adalah proses belajar pada dalang terkenal seniornya yang mereka anggap sebagai guru dalang. Karena sifat proses belajarnya kekeluargaan, maka model “nyantrik” atau “ngenger” bisa dilakukan secara luwes dalam soal waktu dan suasana. Tetapi yang terjadi pada dua tokoh dalang maestro di atas, berguru sampai bertahun-tahun, berpindah-pindah pada beberapa guru, termasuk pada keluarganya sendiri.
Dua dalang maestro (Ki Anom Suroto dan Ki Manteb Soedharsono), dalam pengakuan masing-masing dalam buku yang pernah disusun penulis, punya latar belakang pendidikan umum (STM dan SMA). Tetapi, karena jalan hidup yang dipilih adalah profesi dalang untuk meneladani para leluhur mereka, maka “nyantrik” dan “ngenger” menjadi pilihan utama untuk mengumpulkan modal dan menguasai pengetahuan seni pedalangan.
Tetapi keduanya tahu, bahwa para pendahulunya banyak yang mendapatkan modal pengetahuan pedalangan langsung atau tidak langsung dari Kraton Mataram Surakarta. Maka, tidak aneh kalau Ki Anom Surata juga belajar mendalang di Sanggar Pawiyatan Dalang Kraton (Mataram) Surakarta dan di Himpunan Budaya Surakarta (HBS) tahun 1970-an, sedangkan Ki Manteb belajar di Pasinaon Dalang Mangkunegaran (PDMN).

Krisis di berbagai bidang yang mengguncang stabilitas nasional yang menumbangkan rezim Orde Baru di tahun 1998, ternyata juga semakin memperburuk nasib berbagai seni tradisional, termasuk seni pertunjukan wayang kulit yang punya label “gagrag” Surakarta yang merujuk nama besar Kraton Mataram Surakarta. Karena bersamaan masuknya “angin kebebasan”, berhembus pula anasir-anasir ekstrem, intoleran, anarkis.
Di saat itulah, berbagai jenis kesedian tradisional yang berbasis Budaya Jawa mengalami tekanan berat karena dianggap musyrik, syirik dan bit’ah. Salah satu stigma negatif diberikan, karena pentas wayang dijadikan ekspresi bercanda berlebihan, urakan dan “misuh-misuh” yang melewati batas etika, yang bertolak-belakang dengan sifat “tuntunan” esensi wayang. Dua maestro dalang itu jelas ikut “terpukul”.
“Pasar” bagi dua maestro dalang itu tentu semakin sempit karena kehilangan penanggap karena berbagai sebab, di antaranya sudah “menjadi golongan religius”. Di sini sangat kelihatan, bahwa dua maestro itu sedang ditinggal “pasar tanggapan”, setelah 20-an tahun memberinya “rezeki berlimpah”. Keduanya jelas “tidak nyaman” untuk terus “konsisten” di jalur klasik, padahal terlanjur masuk ke industri seni. (Won Poerwono – bersambung/i1)