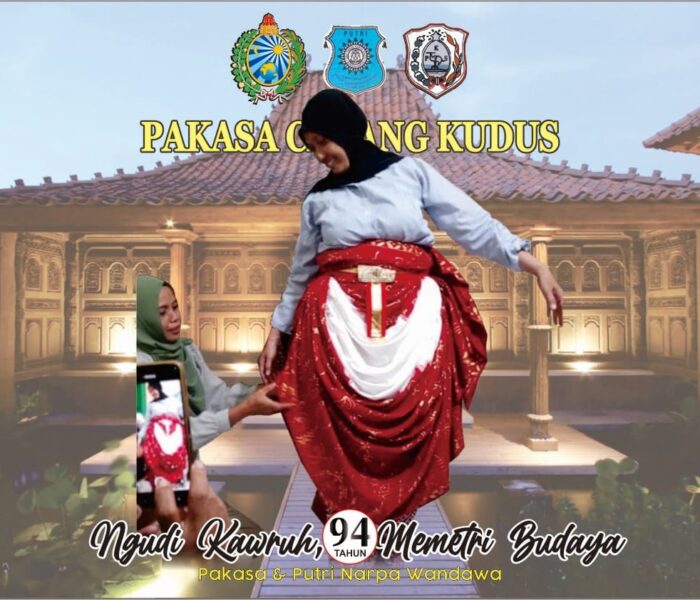Generasi Dalang Muda rata-rata Miskin Nilai Kapujanggan dan Pengetahuan Umum
IMNEWS.ID – “KEPERGIAN” dua maestro dalang yang masih konsisten pada nilai-nilai idealistik mampu “menggelar” sekaligus “menggulung jagad pakeliran”, berarti generasi sumber informasi di luar lembaga pendidikan soal esensi seni pedalangan sudah langka, bahkan habis. Tetapi mungkin saja masih ada lembaga akademis jenjang perguruan tinggi yang mengajarkan pengetahuan tentang “filsafat” seni pedalangan itu.
“Filsafat” seni pedalangan, mungkin juga menjadi satu dengan pengetahuan tentang nilai-nilai etika dan estetika, atau diberikan secara terpisah. Dua maestro dalang, Ki Anom Suroto dan Ki Manteb Soedharsono dan generasi seusianya, nyaris tak ada yang menempuh pendidikan secara khusus tentang seni pedalangan, khususnya pengetahuan filsafat dan tata-nilai seni pedalangan. Karena, hanya didapat dari “nyantrik”.

Proses transfer pengetahuan seni pedalangan juga semua hal yang tercakup dalam nilai-nilai “kautaman” atau “kapujanggan”, hanya mereka dapat dari “nyantrik” atau “ngenger” pada guru dalang atau tokoh spiritual religi. Karena, pendidikan formal yang mereka tempuh adalah bangku sekolah umum yang jelas tidak mengajarkan pengetahuan seni pedalangan seperti di Sekolah Menengah Kejuruan (SMKI) seni.
Kedua almarhum maestro dalang itu, masih sering memberi edukasi tentang nilai-nilai filsafat kehidupan, nilai-nilai “kautaman” dan “kapujanggan”. Tetapi, karena menonjolnya ketokohan dan nama besar keduanya justru sering dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak enak mirip pepatah “buah simalakama”. Di sela-sela padatnya jadwal pentas, banyak yang “memaksanya” untuk melanggar nilai-nilai “kautaman”.
Nilai-nilai “kautaman” dan “kapujanggan” yang sering mereka langgar, karena menjadi satu paket dengan nilai kontrak pentas yang tentu fantastik nilainya untuk “pasar” seni pedalangan. Sampai di tahun 2010 bahkan lebih, ketika ada yang “nanggap” (mengundang pentas) dengan nilai Rp 150 juta – Rp 250 juta untuk sekali pentas yang lokasinya di kota besar walau jarak 300-500 KM, nilai job itu jelas “fantastik”.
Bukan hanya soal nilai job yang fantastik, tetapi pesan atau permintaan yang terselip dalam kontrak pentas itu yang menjadi inti hal penting untuk dicermati. Yaitu, permintaan untuk menerima unsur lain atau “bintang tamu” ke dalam pentas seni pakeliran yang “digelarnya”. Artinya, “jagad pakeliran” yang digelar harus mau dimasuki unsur “seni” lain dari bintang tamu yang dihadirkan tuan rumah “penanggap”.

Bintang tamu yang sudah sering masuk di pertunjukan seni pedalangan, adalah perorangan/grup lawak, penyanyi pop/dangdut, instrumen musik lain juga grupnya dan penari atau pesinden “crew” dalang yang “diperintah” berdiri di atas atau di bawah panggung untuk berjoget. Dua almarhum maestro dalang itu juga sering melakukan “eksperimen” melanggar nilai-nilai etika itu, tetapi rata-rata berdalih “terpaksa”.
“Terpaksa” yang dimaksud adalah permintaan yang menjadi satu paket dengan nilai kontrak yang disepakati anatar dalang penyaji beserta kelompoknya dan tuan rumah “penanggap” (pengundang pentas). Daya nalar publik secara luas khususnya kalangan seniman, terlebih dalang, mendapat tawaran pentas senilai Rp 150 juta-Rp 250 juta sesuai ukuran di atas di saat-saat popularitas mulai meredup, nilai itu sangat berarti.

Tidak hanya masalah “terpaksa” dan popularitas yang meredup, frekuensi job pentas yang terus menurun akibat wayang kulit dituding musyrik, syirik dan tak ada manfaatnya, nilai job itu menjadi fantastik. Apalagi, jika keduanya masih aktif di saat “daya beli” rakyat anjlok karena krisis multi dimensi global, kini. Kalaupun si dalang harus “berjoget sambil jungkir-balik” di panggung, mungkin “bisa” dituruti.
Ketika dianalisis lebih jauh, dua maestro dalang yang notabene sosok panutan yang disegani, senior yang diteladani, punya popularitas tinggi dan sukses secara ekonomi tetapi “bisa” hanyut ke arus penyajian yang melanggar, bagaimana dengan generasi dalang di bawahnya?. Ada dua dalang generasi di bawah dua maestro itu, yaitu Ki Purbo Asmoro dan Ki Warseno Slenk (alm) yang sama-sama mengenyam perguruan tinggi.
Ki Purbo Asmoro adalah dosen di Jurusan Pedalangan ISI Surakarta, selain dalang profesional yang juga punya popularitas tinggi. Tetapi karena mantan Ketua Pepadi Surakarta (2014-2019) di kampus dan di luar sering terlibat diskusi dengan berbagai disiplin ilmu, kualitas estetika, etika dan pemahaman nilai-nilai “kapujanggan” sangat baik. Dia bisa mengedukasi tentang nilai-nilai “kautaman” pada publik.
Tetapi, kelihatannya tidak begitu arah perjalanan profesi kesenimanan Ki Warseno Slenk. Walau sempat meraih gelar “Doktor” pada disiplin ilmu non-pedalangan, tetapi sepanjang pengamatan iMNews.id, bahkan saat di harian Suara Merdeka, almarhum nyaris tidak memperlihatkan level intelektualitas yang diraih. Edukasi publik tentang nilai-nilai “kautaman” dan “kapujanggan” tetap tidak tampak pada profesinya.

Ketika mencermati peta keberadaan potensi dalang yang masih memiliki kemampuan mengedukasi tentang nilai-nilai idealistik di atas, maka menjadi sangat wajar situasi dan kondisi wayang kulit bernasib “buruk” seperti sekarang. Karena, hampir semua dalang di bawah generasi Ki Anom Suroto dan Ki Manteb Soedharsono, sulit diharapkan bisa menjaga nilai-nilai wayang sebagai “tuntunan” selain “tontonan”.
Walau banyak praktisi profesi dalang berlatar akademisi (ISI Surakarta dan Jogja), ternyata belum menjamin sajian wayang kulit menjadi sarana ideal, untuk merawat kehidupan peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai “kautaman”. Yang terjadi, rata-rata dalang bahkan yang akademisi, malah hanyut ke dalam arus penyajian yang menuruti “selera pasar” atau industri seni, mengorbankan nilai-nilai ideal.

Karena para dalang praktisi profesi termasuk akademisi memilih menurutu selera pasar demi popularitas yang maknanya “laris”, maka saat itulah seni pertunjukan wayang kulit kehilangan sifat utamanya sebagai “tuntunan”. Karena, nilai-nilai tuntunan dalam “jagad pekeliran” adalah bimbingan edukatif dalang level “brahmana” atau “pujangga”, yang selalu menawarkan nilai-nilai “kautaman-ing urip” dan “kapujanggan”.
Persoalannya, generasi dalang di bawah generasi Ki Anom Suroto dan Ki Manteb Soedharsono, nyaris tidak ada yang mencoba belajar “kawruh kabrahmanan” dan “kapujanggan”. Jadi, sebagian besar praktisi profesi dalang bahkan tidak mengenal makna nilai-nilai “kautaman” dan “kapujanggan”. Karena yang dipelajari dan dipraktikkan, adalah teknis mendalang praktis dan pragmatis serta daya tarik panggung di luar dirinya. (Won Poerwono – bersambung/i1)