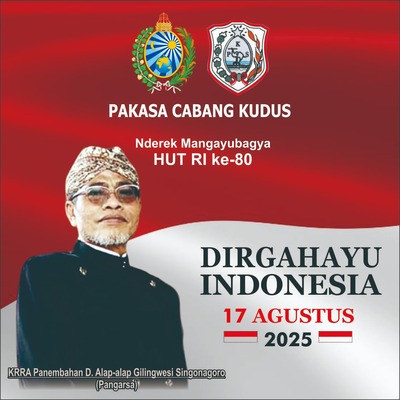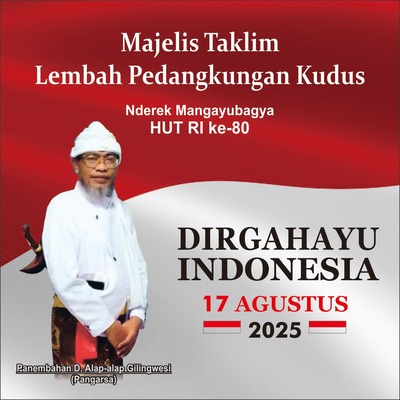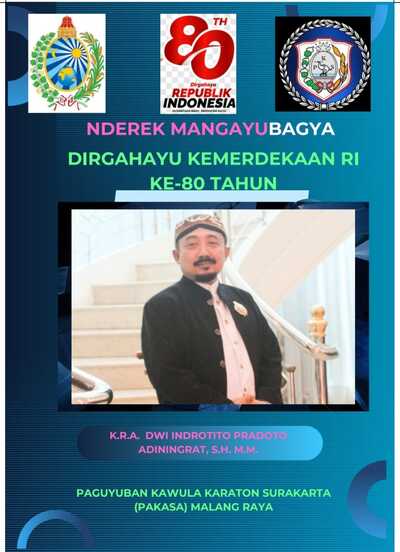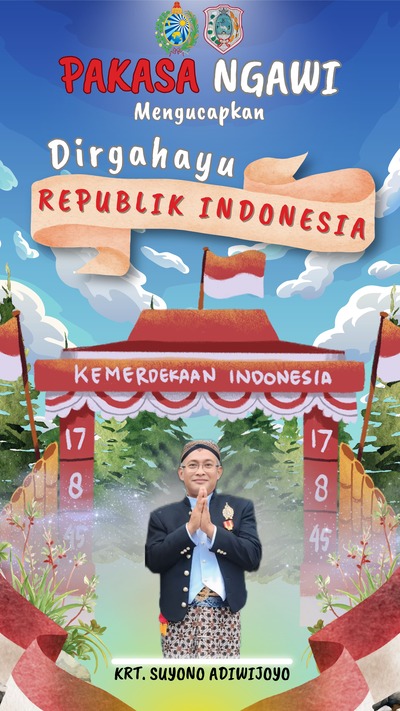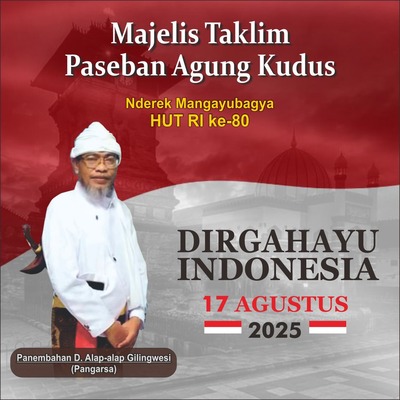Sudah Sepantasnya Dipertanyakan Pihak Otoritas Kraton Mataram Surakarta
IMNEWS.ID – PRINSIP-PRINSIP dalam kehidupan peradaban yang penuh tata-nilai adat dan kearifan lokal budayanya, sebenarnya sudah menjadi salah satu ciri hubungan sosial secara apapun di masa lalu. Terutama, dalam hubungan sosial kemasyarakatan maupun secara adat di lingkungan “negara” (monarki) Mataram Islam yang sudah memiliki landasan fundamental Budaya Jawa dalam kehidupannya.
Tetapi memang, suasana kehidupan pada abad-abad antara 14-18 adalah tahap perkembangan kehidupan sosial yang belum menempatkan hak dan kewajiban sebagai sesuatu yang harus diberikan secara penuh, secara seimbang dan jelas betul bedanya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang mulai ditegakkan di negara-negara barat, baru dirumuskan menjadi sebuah aturan internaional pada 1-2 abad kemudian.
Meski Indonesia baru mengenal prinsip-prinsip HAM sejak terdaftar sebagai anggota PBB, tetapi di lingkungan masyarakat komunal Budaya Jawa, prinsip-prinsip menghargai hak dan kewajiban sudah dimiliki sebagai bagian dari kearifan lokalnya. “Ngajeni marang sasama lan ngajeni marang sagunging titah”, sudah dimiliki “wong” Jawa sebagai prinsip berkehidupan pribadi dan sosialnya, sejak peradaban Jawa ada.
Karena HAM baru dikenal sejak NKRI terdaftar sebagai anggota PBB, tentu saja ada jenis hak lain dan tuntutan yang menjadi keseimbangan disebut “kewajiban” itu, juga menjadi hal baru bagi masyarakat bangsa secara nasional. Pengakuan atau penghargaan terhadap eksistensi asasi pribadi yang disebut hak, begitu pula sesuatu “tuntutan” yang harus dilakukan kepada “ruang” di luar pribadinya, harus diberikan.

Bila melihat konstruksi antara “hak” dan “kewajiban” yang harus sama-sama diberikan atau dimiliki, di situ menjadi prinsip keseimbangan. Hak yang harus didapat/dipenuhi, dan kewajiban yang harus dilakukan atau diberikan sejak NKRI meratifikasi Konvensi HAM, harus dimiliki setiap insan secara seimbang. Bila negara “menjaga” keseimbangan antara hak dan kewajiban, seharusnya rasa keadilan “terpenuhi”.
Melihat perkembangan secara umum, beberapa hal terakhir itulah kini menjadi salah satu persoalan yang dihadapi NKRI. Padahal, persoalan itu sangat fundamental yang “harus dimiliki setiap insan” bangsa di Nusantara ini, secara merata dan “setara” atau “memenuhi rasa keadilan”. Agaknya, sifat-sifat kearifan budaya bangsa, khususnya Budaya Jawa yang sangat “permisif”, dimaknai sebagai “permakluman”.
“Sikap maklum” masyarakat (adat) pemilik Budaya Jawa terhadap “rasa keadilan” yang selama ini “didambakan”, menjadi kata kunci yang terkesan “terabaikan”. Karena, selama ini penguasa terkesan “mengkaburkan” soal hak, tetapi melakukan “rekayasa” aturan untuk menuntut kewajiban insan bangsa ini. Maka, tidak berlebihan kalau belakangan muncul aksi dan reaksi dari insan bangsa di berbagai daerah.
Karena, penguasa terkesan begitu “culika” menciptakan sistem penekan untuk menagih kewajiban rakyat membayar pajak sampai ratusan persen. Kemudian, dibalas dengan aksi demo untuk menolak “agihan” pajak yang jauh dari prinsip-prinsip rasa keadilan itu. Bahkan, ada pula ekspresi kalangan “industri seni budaya” yang menuntut “penghargaan” (nilai) royalti dari Hak Cipta atas karyanya.

“Sikap maklum” masyarakat adat terhadap “perampasan” hak dan rasa keadilan itu, ternyata justru dimaknai “keliru” oleh seorang pejabat Dirjen Perlindungan Kebudayaan Kemenbud. Dia menggunakan logika terbalik untuk menguatkan definisi “permakluman”, bahwa para leluhur (nenek moyang Jawa-Red) sangat baik hati atau bermurah hati, karena tidak mau mencantumkan “label” atau “nama” pada karya seni-budayanya.
Ungkapan seperti itu, diberikan pejabat tersebut di forum seminar/sarasehan budaya yang diinisiasi Bebadan Kabinet 2004 pimpinan GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng. Forum sosialisasi dan diskusi yang digelar di Sasana Handrawina (iMNews, 23/8), menyajikan karya seni tari “Srimpi Lobong” (Sinuhun PB VIII) dan dihadiri undangan yang belum sepenuhnya “representatif” lembaga terkait.
Namun, forum yang membahas nasib berbagai karya seni produk Budaya Jawa oleh beberapa tokoh narasumber selain Gusti Moeng sebagai pembicara, siang itu, patut diapresiasi. Karena, “keberanian” mempersoalkan “nasib” karya-karya seni budaya para luluhur, datang dari lingkungan masyarakat adat. Padahal, selama ini penguasa meyakini, “ekspresi” itu tidak akan muncul karena dianggap hal yang tabu.
Tetapi, prinsip-prinsip kesetaraan dalam mendapatkan rasa keadilan, harus ditegakkan siapapun, termasuk dari lingkungan masyarakat adat. Karena, mereka juga warga negara asli (WNI), bahkan para leluhurnya banyak berjasa dalam mendirikan NKRI. Karya-karya seni budayanya, jelas ikut membentuk watak dan cirikhas pribadi bangsa ini, namun “diperlakukan” dengan cara yang jauh dari rasa keadilan.

Momentum munculnya ekspresi menuntut penghargaan atas Hak Cipta karya seni budaya itulah, yang ikut menggelitik lembaga masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta. GKR Wandansari Koes Moertiyah selaku Ketua (Pangarsa) Lembaga Dewan Adat (LDA), merasa didorong memberanikan diri mempersoalkan “rasa keadilan”, karena banyak karya seni budaya para tokoh dan atas nama lembaga masyarakat adat, “dibajak”.
Pernyataan Dirjen Perlindungan Kebudayaan di atas, juga menganalogikan bahwa banyak karya seni budaya yang tak diberi label atau identitas nama, dikatagorikan sebagai karya “Folklore”. Di satu sisi, itu bisa dimaklumi, karena yang bersangkutan pejabat pemerintah. Sedangkan NKRI, juga mengukiti “aturan” konvensi hak cipta internasional yang “disponsori google”, yang memiliki “segala batasan” itu.
Karena dianggap “folklore” dan setiap “konten” (YouTube, IG, Twiter dsb) yang diunggah dianggap “google” sebagai pemilik “Hak Cipta”, maka di sinilah “nasib” karya-karya luhur dan adiluhung produk para leluhur khususnya Mataram Surakarta, menjadi “korban”. Publik “memaknai” karya-karya “no name” (NN) atau hanya bertitel “zaman jumeneng”, lalu diartikan boleh “dirampas” atau diklaim sebagai karya pribadinya.
Maka, bersamaan dengan itu menjadi sangat kelihatan “kedunguan” para pembuat konten yang mengunggah di berbagai platform media sosial. Mungkin saja bukan “dungu”, tetapi menganggap atau pura-pura tidak tahu bahwa karya seni yang hanya diberi kode “no name” atau hanya bertitel “semasa jumenengnya” Sinuhun Paku Buwana (PB) itu, bisa diakui atau diklaim (dibajak) begitu saja sebagai karya pribadinya.

Karena, semua penjelasan Gusti Moeng tentang karya-karya seni budaya baik musik karawitan, Santi Swara (Laras Madya), tari, pedalangan dan karya sastra, Bahasa Jawa, kosa-kata, motif batik, ritual pengantin dan banyak sekali yang berkait dengan bidang kehidupan “wong” Jawa, “sudah ada” jauh sebelum ada NKRI. Lembaga “negara” (monarki) Mataram Surakarta, punya otoritas atas status hak kepemilikannya.
“Sudah ada”, harus dimaknai “ada” yang menciptakan, setidaknya bentuk bakunya. Padahal, berbagai jenis seni produk Budaya Jawa, rata-rata utuh, lengkap dan sudah selesai final, yang sering disebut “puncak-puncak kebudayaan”. Pada zaman kraton, hampir semua karya seni menjadi daya dukung legitimasi upacara adat dan lembaga. Maka, hampir semua karya merujuk pada nama lembaga dan zaman tokoh yang jumeneng. (Won Poerwono – bersambung/i1)