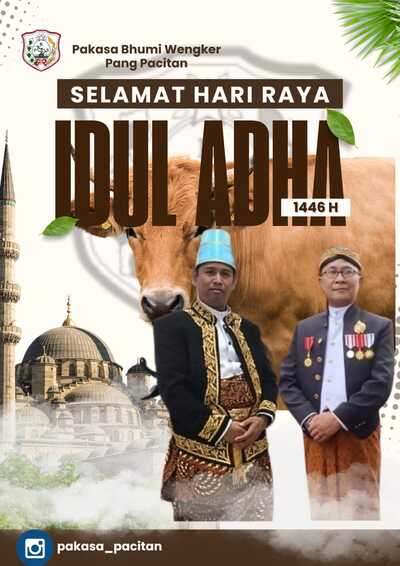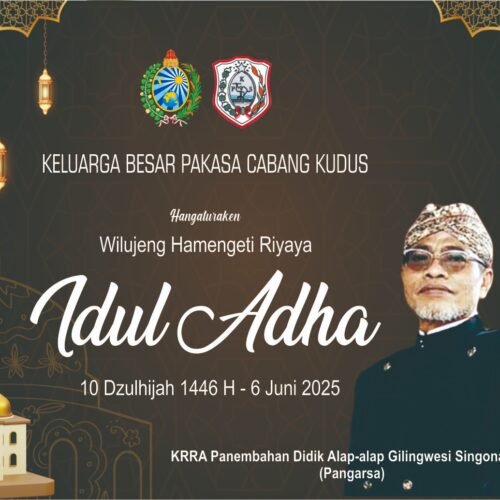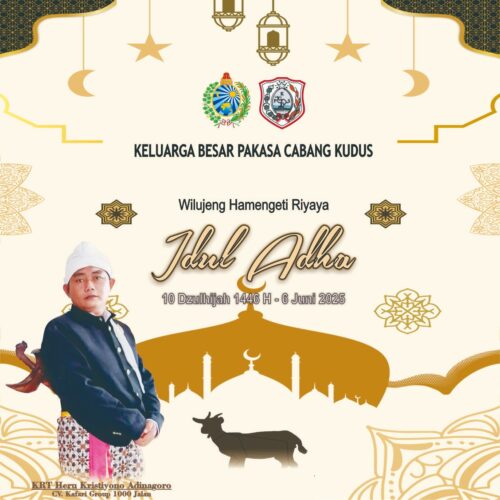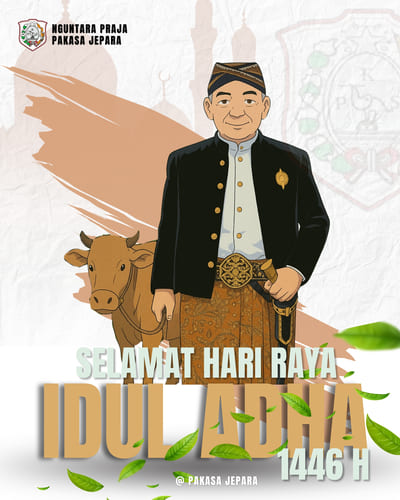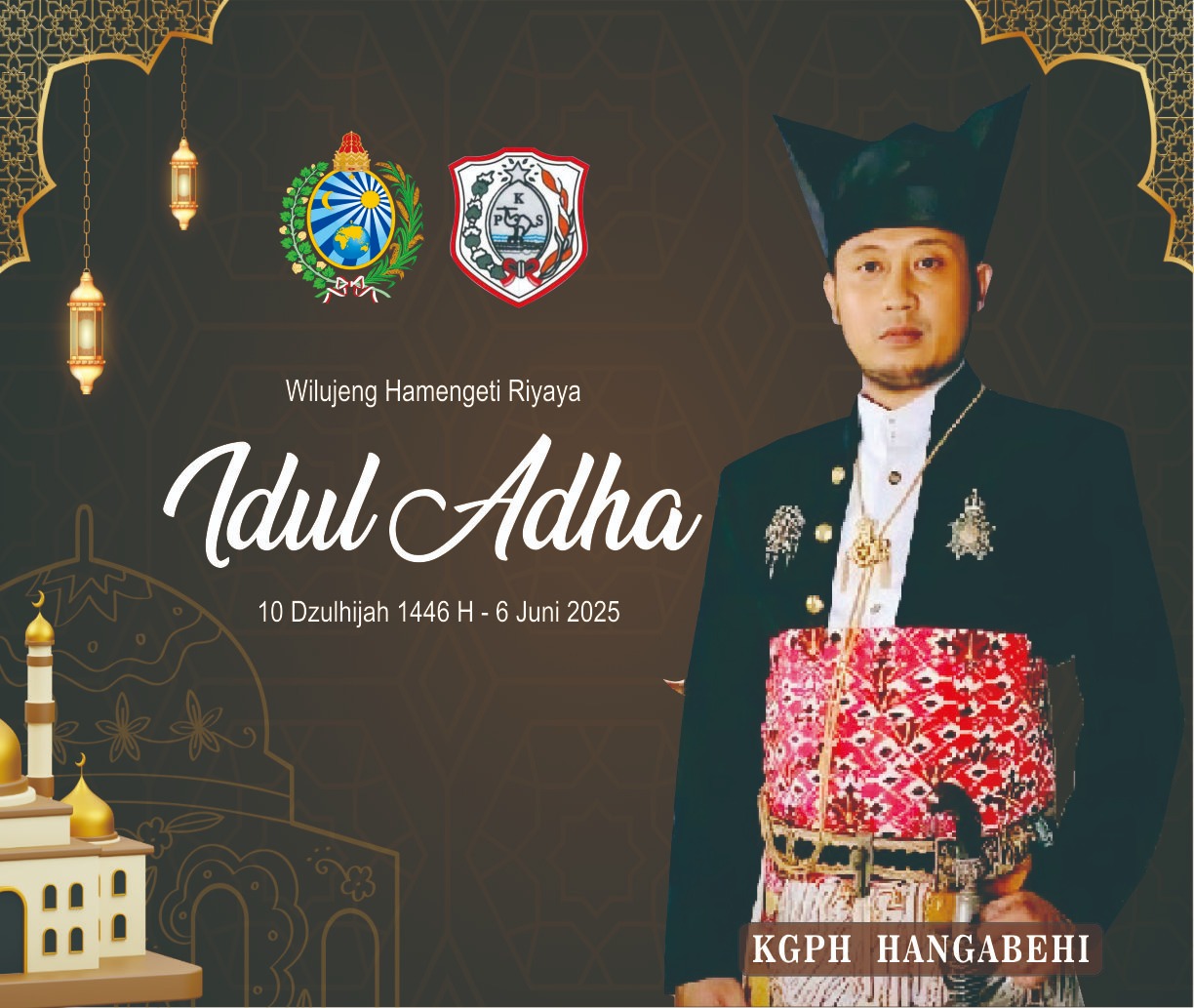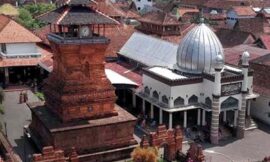Putri Narpa Wandawa Simbol Peran dan “Militansi” Para Tokoh “Wanita Mataram”
IMNEWS.ID – DARI seri tulisan sebelum ini (iMNews.id, 8/6) dan tema-tema lain artikel yang tampil di media ini, sudah banyak menampilkan contoh-contoh bagaimana publik secara luas begitu awam terhadap eksistensi “Karaton” Mataram Surakarta. Generasi yang semakin “jauh” dari peristiwa 1945, bahkan “sudah buta” terhadap sejarah masa lalu leluhur bangsa ini.
Kraton Mataram Surakarta hanya dipandang sebagai “museum mati”, sekadar lembaga seni budaya atau lembaga kerajaan seperti yang sering dilukiskan dalam drama ketoprak yang hanya dihiasi intrik, sentimen, “gandrung” dan perang. Banyak yang mengira Negara Kesatuan RI (NKRI) hanya sekadar “diperjuangkan” dengan merintis kemerdekaan dan serangkaian aksi perang.
Banyak yang tak mengira, bahwa “proses perjuangan” merintis kemerdekaan dan aksi perang itu terjadi di dalam negara-negara kecil yang umumnya “monarki” yang tersebar di Nusantara. Negara (monarki) terakhir terbesar dan modern saat itu, adalah negara (Karaton) Mataram Surakarta yang berada di Jawa, karena beberapa yang lain lebih kecil dan punya sikap “berbeda”.
Negara-negara (monarki) kecil yang ada di Nusantara dan banyak yang di luar Jawa, memang jauh berbeda bila dibanding Kraton Mataram Surakarta dalam konteks kelengkapan syarat sebagai negara, apalagi mengacu “Trias Politica”. Bahkan, rata-rata belum tersentuh angin demokratisasi selepas PD I dan II yang ditandai dengan kebebasan berserikat dan “berekspresi”.

Sedangkan “negara-negara” kecil yang ada di Jawa waktu menjelang 1945, adalah beberapa kraton di wilayah Cirebon (Jabar), Kraton (Kesultanan) Jogja dan dua “Kadipaten” yaitu Pura Pakualaman (Jogja) dan Pura Mangkunegaran (Surakarta). Beberapa kraton di Cirebon dan Kesultanan Jogja, jauh dari “terminologi” negara, apalagi dua “Kadipaten” yang jelas “bukan kraton”.
Pemahaman dalam konteks negara pula, yang sebenarnya menjadi dasar bahwa “penyerahan kekuasaan” pada momentum pembacaan teks Proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta, ketika dianalisis terjadi dari “negara” (lama) ke “negara” baru. Bung Karno dan Bung Hatta mewakili “negara” baru NKRI, sedangkan “negara” lama tak jelas siapa yang ditunjuk mewakilinya.
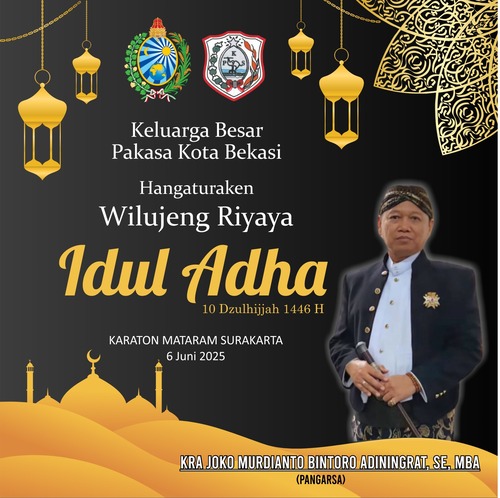
Analisis kritis lebih lanjut bisa menyebut “penyerahan kekuasaan” seperti yang disebut di bagian akhir teks Proklamasi, lebih rasional terjadi dari “negara lama” yang jelas merujuk ke Karaton Mataram Surakarta. Karena, posisinya sebagai “negara” terakhir terbesar di Nusantara, yang posisinya ada di Jawa yang menjadi ajang dan pusat rintisan kemerdekaan RI.
Namun, boleh saja publik berpendapat bahwa “penyerahan kekuasaan” ke tangan Bung Karno dan Bung Hatta yang mewakili NKRI, dilakukan Belanda atau Jepang yang saat itu masih bercokol menguasai “sebagian” kekuasaan di Nusantara. Karena, senyatanya hingga saat ini memang tidak pernah ada “penjelasan” soal detil-detil proses itu dari negara kepada bangsa atau rakyatnya.

Sampai di situ pemahaman soal status dan posisi “Karaton” Mataram Islam Surakarta dalam terminologi “negara” (monarki), sudah sangat jelas. Karena, hampir semua persyaratannya sudah terpenuhi, baik pemisahan kekuasaan sesuai “Trias Politica” maupun beberapa syarat tambahan menuju suasana negara demokrasi, yaitu kebebasan berserikat dan kebebasan “berbicara”.
Salah satu syarat kebebasan berserikat itu, adalah terbentuknya berbagai organisasi sosial sebagai sarana menghimpun dan melahirkan aspirasi melalui kebebasan “berekspresi” atau “berbicara”. Negara (monarki) Mataram Surakarta mulai zaman Sinuhun PB X, telah melahirkan banyak organisasi sosial dan politik yang terarah pada pergerakan “merintis kemerdekaan”.
Lahirnya berbagai organisasi sosial, kemasyarakatan dan politik dalam kerangka kebebasan “berserikat” inilah, yang sepertinya tak pernah lahir di beberapa kraton dan “Kadipaten” itu. Dan wujud dari kebebasan “berserikat” inilah yang menjadi salah satu syarat terminologi “negara” selain persyaratan lain seperti yang disebut dalam “Trias Politica”.
Oleh karena itu, keberadaan Putri Narpa Wandawa di antara beberapa organisasi yang lahir dari internal “negara” (monarki) Mataram Surakarta, sangat layak bahkan wajib dipahami publik secara luas. Bahwa kelahirannya pada 5 Juni 1931 dan sepak-terjangnya dalam pergerakan merintis kemerdekaan hingga pasca-17 Agustus 1945, hingga kini, adalah fakta jejak sejarah.

Fakta jejak sejarah Mataram Surakarta itu tidak bisa dihapus. Begitu juga peran dan jasanya dalam mewarnai pergerakan merintis kemerdekaan RI. Meskipun, perannya disalurkan melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), tetapi itulah fakta sepak-terjang organisasi wanita, yang tentu diinspirasi oleh para individu tokoh wanita sebelumnya.
Sepak-terjang Putri Narpa Wandawa jelas berkait dengan kebebasan “berserikat” bagi siapa saja, termasuk kaum perempuan, terutama dalam upaya merintis kemerdekaan, waktu itu. Aktivitas pergerakan mereka adalah fakta sejarah yang tak bisa dihapus, karena banyak tokoh lain di berbagai organisasi di lingkaran aktivitas merintis kemerdekaan, yang saat itu eksis.
Selain kepada Budi Utomo, tokoh Putri Narpa Wandawa banyak menyalurkan aspirasi ke BPUPK. Karena Sinuhun PB XI telah menugaskan KRT Dr Radjiman Wedyadiningrat untuk “menginisiasi” persiapan kemerdekaan bersama 78 anggota BPUPK (I-Red). KRT Dr Radjiman Wedyodiningrat adalah abdi-dalem yang pernah menjabat Ketua Budi Utomo itu, Ketua BPUPK sampai sebelum ada PPK (I).
KRAy Koes Sapariyah yang bergelar GKR Paku Buwana saat menjadi “prameswari-dalem” Sinuhun PB XI, menjabat Ketua I di awal kelahiran Putri Narpa Wandawa, 5 Juni 1931. Dia adalah tokoh “Wanita Mataram” yang muncul kemudian setelah RA Kartini (1879-1904), putri seorang Bupati Jepara pada saat “negara” (monarki) Mataram Surakarta dipimpin Sinuhun PB X (1893-1939).

Walau RA Kartini “diabadikan” sebagai tokoh wanita pejuang kesetaraan gender “Habis Gelap Terbitlah Terang” di berbagai buku pelajaran sejarah di berbagai tingkatan sekolah di zaman Orde Baru, tetapi peran dan jasa besar KRAy Koes Sapariyah “tak terhapus” begitu saja. Fakta tentang ketokohannya memimpin “serikat” Putri Narpa Wandawa, “tak bisa dihapus”.
Tak hanya “prameswari-dalem” Sinuhun PB XI itu, peran dan jasa istri Patih-dalem KRMT Sasradiningrat V dan istri Patih KRMT Wuryaningrat, juga “tak bisa dihapus”. Dalam menjelaskan buku “Biografi Sinuhun PB XI” karyanya, Dr Purwadi menyebut, nyonya Wuryaningrat (konglomerat/pengusaha batik), yang menyumbang konsumsi gratis selama BPUPK bersidang, 23/5-13/8/1945. (Won Poerwono – bersambung/i1)