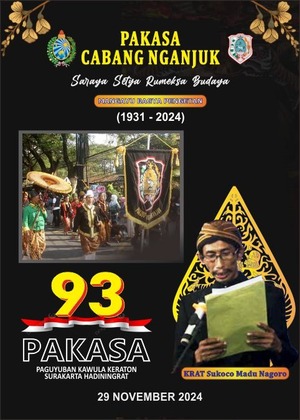Sentimen, Apriori dan Antipati Pada Para Leluhurnya Sendiri, Akibat “Pageblug Penalaran Sehat”
IMNEWS.ID – ARTIKEL seri sebelum ini, ditutup dengan ungkapan yang transendental “Biarlah penggantinya nanti, Sinuhun PB XIV memperbaiki hal-hal buruk pendahulunya”. Karena “orang-orang baik” di belakang Gusti Moeng dan “fans berat” dari berbagai elemen LDA, pasti akan mendukung. Karena, sifat-sifat kepemimpinan Mataram Islam Surakarta masih dibutuhkan.
Tetapi memang sifat-sifat kepemimpinan yang lengkap tersebut di atas jelas sudah tidak memungkinkan untuk dimiliki Sinuhun PB XIV dan para penerusnya. Karena Kraton Mataram Surakarta sudah bukan lagi lembaga negara dan pemerintahan. Tetapi, menjadi pemimpin adat, penjaga budaya, pemimpin masyarakat adat dan pemimpin peradaban masih diperlukan.
Beberapa sifat kepemimpinan yang tersisa itu, sangat penting untuk terus dipertahankan dan menjadi ciri pemimpin Mataram Surakarta, sampai kapanpun. Karena, itulah bentuk komitmen yang menjadi cirikhas pemimpin Mataram di satu sisi. Dan di sisi lain, itulah bentuk sumbangan keteladanan dan contoh edukasi yang diberikan Mataram kepada publik secara luas.

Dalam kerangka itulah, maka para pemimpin di berbagai tingkatan di NKRI ini, diharapkan bisa meneladani dan mencontoh sifat-sifat kepemimpinan itu, kecuali yang “lahir” di masa “pageblug” (2004). Pemimpin yang beretika, santun, satu kata dan perbuatan, selalu menjalankan amanat konstitusi (aturan) dan menggenggam erat makna “Jasmerah”, itu yang dibutuhkan.
Jangan mencontoh pemimpin yang baru saja lengser setelah 10 tahun bertahta, karena sama sekali tidak bisa mewakili sifat-sifat kepemimpinan Jawa, apalagi Mataram. Penuh rekayasa, kehilangan etika dan ternyata bukan tipe pemimpin yang patuh terhadap “Jasmerah”, karena bicaranya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu atau “esuk dhele, sore tempe”.
Kalau mencermati situasi dan kondisi Kraton Mataram Surakarta yang sedang dilanda “pageblug” atau hilangnya sifat-sifat kepemimpinan, rasanya tidak jauh dari situasi dan kondisi di luar kraton atau di republik ini. Karena, sejak NKRI lahir, para pemimpinnya banyak mengindikasikan “pageblug kepemimpinan”, yang melahirkan generasi pemimpin berciri-ciri sama.
Slogan dan semangat “Jasmerah” yang berkali-kali ditandaskan Bung Karno dalam berbagai kesempatan berpidato sebagai pencetus ide, ternyata juga tidak sepenuhnya menjadi pesan bijak ideal dan penuh moral. Di era kepemimpinan rezim Orde Baru, pesan moral itu lenyap terkubur dan baru muncul lagi di era reformasi 1998, dan kembali lenyap setelah itu.
Lenyapnya pesan moral “Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah” yang dianggap identik dengan partai tertentu itu, lebih mirip salah satu cerminan pada masa “pageblug sifat-sifat kepemimpinan, bertolak-belakang dengan tokoh leluhur Mataram, terutama Surakarta. Karena sebenarnya, yang terjadi sejak NKRI ini lahir adalah “pageblug penalaran” dan “etika”.
Karena sesuatu, seorang pemimpin dan kelompoknya menjadi tidak bisa menggunakan akal sehat dan nuraninya dengan baik dan tepat serta ideal. Itulah “pageblug penalaran dan etika” yang sesungguhnya terjadi di republik ini, selama ini. Akibat itulah tidak aneh, ruang Kota Surakarta justru dipenuhi nama-nama “pahlawan” tidak dikenal dan “tidak bisa diteladani”.

“Pageblug penalaran” dan “etika” bisa terwujud dalam sikap dan pemikiran yang apriori, sentimen negatif/positif dan antipati terhadap seorang atau kelompok tertentu termasuk peradabannya. Contoh peradaban, para tokohnya dan karya-karya pemikiran yang menjadi korban para penderita “pageblug penalaran” dan “etika” itu adalah ruang Kota Surakarta.
Dengan melihat ruang Kota Surakarta bisa terlihat jelas, bahwa ada pribadi tokoh, kelompok atau generasinya yang menderita “pageblug penalaran” dan etika” telah mengkhianati “komitmennya”. Komitmen sebagai generasi pewaris dan penerus nilai-nilai luhur para pendahulunya, sampai tega meniadakan, merusak dan merubah nilai-nilai warisan pendahulu.
Karena prosesnya seperti itu, maka tidak aneh kalau ruang Kota Surakarta justru dipenuhi bangunan baru yang dijadikan ikon, tetapi jauh dari nilai filosofi fundamental Surakarta sebagai pusatnya Budaya Jawa. Ruang Kota Budaya ini malah dipenuhi patung tokoh, yang jauh dari jasa-jasa di bidang Budaya Jawa, dan jauh dari sifat-sifat kepemimpinan Mataram.
“Keris di masa damai, wong Jawa selalu menempatkannya di punggung, agar tidak menjadi ancaman (psikologis) bagi orang lain. Tetapi, lain dengan generasi zaman sekarang. Walaupun damai, keris diperlihatkan dalam keadaan terhunus. Etika wong Jawa menyebut itu arogan, menantang atau simbol suasana perang. Karena, wong Jawa pantang menunjukkan kesaktiannya.
“Sesuai paugeran di kraton dan juga praktik kehidupan masyarakat Jawa, keris menjadi simbol atau alat komunikasi selain pusaka dan kelengkapan busana adat. Kalau disengkelit di belakang, maknanya simbol kepatuhan kawula dan Bupati kepada Rajanya. Tetapi kalau di depan, itu diartikan sedang menunjukkan sikap perlawanan, bahkan hendak memberontak Raja”.
“Selain simbol kepatuhan, keris yang diletakkan di punggung, juga untuk menjaga kenyamanan si pemakai saat berjalan membebek (jongkok) atau ‘laku dhodhok’ dalam pisowanan menghadap Raja. Keris tetap indah dikenakan orang pemakai jas ‘krowokan’ atau Langenharjan,” ujar KPP Nanang Soesilo Sindoeseno Tjokronagoro saat dimintai konfirmasi iMNews.id.

Sentana darah-dalem trah Sinuhun PB X dan PB V itu tidak menyebut langsung bahwa keris yang terhunus atau “linigan” yang dimaksud adalah monumen berupa petung keris yang dipasang Pemkot Surakarta di kanan-kiri jembatan Tirtonadi, dekat terminal bus induk Gilingan, Kecamatan Banjarsari. Tetapi, konotasi penjelasannya tertuju pada patung yang “menantang” itu.
Sentana-dalem itu juga salah satu representasi masyarakat adat Kraton Mataram Surakarta yang selama ini mempersoalkan nama-nama jalan dan patung para tokoh yang disebut “pahlawan”, tetapi sama sekali tidak jelas asal-usulnya. Makanya dia menyatakan aneh, Surakarta sebagai Kota Budaya tetapi sedikitpun tidak mencerminkan nilai-nilai Budaya Jawa.
Menurutnya, siapapun yang menjadi pemimpin di Kota Surakarta, seharusnya memahami Budaya Jawa, salah satu nilainya adalah menghormati leluhurnya. Karena, para tokoh Mataram Surakarta yang mewariskan kota ini dengan segala simbolnya. Tetapi, para penderita “pageblug” NKRI lahir sudah berkehendak lain, yaitu ingin agar Mataram musna dari muka bumi. (Won Poerwono -habis/i1)